Oleh Ali Farkhan Tsani, Duta Al-Quds, Redaktur Senior Kantor Berita MINA
Pada tanggal 5 Juni 1967, Israel melancarkan perang yang mengakibatkan pendudukan Yerusalem Timur, Tepi Barat, Jalur Gaza, Sinai (Mesir) dan Dataran Tinggi Golan (Suriah) dalam Perang Enam Hari. Palestina menyebutnya sebagai Hari Naksa.
Naksa atau kemunduran, mengacu pada Perang Enam Hari tahun 1967 tersebut.
Setelah 19 tahun sebelumnya terjadi tragedi yang disebut Hari Nakba (pengusiran), pada tanggal 15 Mei 1948.
Baca Juga: Kritik Radikal Ilan Pappe terhadap Proyek Kolonial Israel
Perang itu membuat Israel mengabaikan batas-batas Garis Hijau yang disepakati sebelumnya, yang dibuat pada gencatan senjata 1949 antara Israel, Mesir, Yordania, Lebanon dan Suriah.
Sejak saat itu, Israel yang didukung kuat oleh Amerika Serikat, memberlakukan pendudukan militer di Tepi Barat dan Jalur Gaza serta menganeksasi Yerusalem Timur, dan mengendalikan sekitar satu juta warga Palestina.
Meskipun Presiden AS saat itu, Lyndon B. Johnson (menjabat 1963-1969) mendesak kedua belah pihak agar tidak menyerang. Namun Israel secara masif memulai pengeboman udara ke wilayah Mesir pada 5 Juni, dengan 200 jet menyerang 18 lapangan terbang, menghancurkan hampir 90 persen dari angkatan udara Mesir. Kemudian menyerang Yordania, Irak, dan Suriah.
Tank-tank dan pasukan Israel merangsek memasuki Semenanjung Sinai dan Jalur Gaza. Sementara tentara Mesir berusaha mempertahankan tanah mereka. Yordania pun melancarkan serangan yang menghadap ke Yerusalem selatan. Namun kedua negara itu terpaksa mundur.
Baca Juga: UNRWA Desak Masuknya Bantuan Tempat Tinggal ke Gaza
Pasukan Israel pun mencapai Dataran Tinggi Golan pada 9 Juni dan merebutnya pada hari berikutnya. Pada 10 Juni, Israel menerima gencatan senjata PBB dan perang berakhir.
Israel secara sepihak segera mulai membangun pemukiman di Tepi Barat, Sinai dan Dataran Tinggi Golan.
Israel kemudian menarik diri dari Sinai pada tahun 1982 dan dari Gaza pada tahun 2005, meskipun tetap mempertahankan kendali atas perbatasannya.
Protes Tahunan
Baca Juga: Bom Israel yang Belum Meledak di Gaza Capai 7.000 Ton
Peristiwa Naksa itu, setiap tahun selalu diingat dengan aksi protes massa di Tepi Barat dan Jalur Gaza menentang pendudukan.
Tahun 2020 ini, pada masa pembatasan pandemi Corona, para aktivis perjuangan bergabunglah dalam aksi protes di media sosial. Kampanye pun marak dengan tagar #Naksa, #StopSettlements, dan #StopAnnexation.
Jaringan Solidaritas Tahanan Palestina Samidoun berbasis di Jalur Gaza pun bergabung dalam kampanye media sosial tersebut
“Kami mendesak semua pendukung Palestina untuk bergabung dengan kami dalam aksi daring ini bersama aksi lainnya untuk menolak aneksasi Israel pada peringatan 53 tahun Naksa.”
Baca Juga: Tim Medis Gaza Berhasil Identifikasi 97 dari 330 Jenazah yang Dikembalikan Israel
“Pembersihan etnis oleh Israel terhadap Palestina masih berlangsung hingga hari ini,” pernyataan Samidoun.
Aksi menyuarakan solidaritas dengan rakyat Palestina dan untuk menolak aneksasi Israel, lanjut pernyataan.
Sementara itu, Dewan Nasional Palestina (PNC) menegaskan menandai 53 tahun Hari Naksa, menjadi penyemangat kelanjutan menghadapi semua proyek konspirasi.
PNC mengatakan dalam sebuah pernyataan di media WAFA News, edisi Kamis, 4 Juni 2020, bahwa tidak ada alternatif untuk mengakhiri pendudukan selain mengembalikan hak-hak yang sah atas kebebasan, kemandirian dan hak untuk kembali, serta pembentukan negara merdeka di sepanjang perbatasan 4 Juni 1967 dengan Yerusalem sebagai ibukotanya.
Baca Juga: Israel Tutup Masjid Ibrahimi di Hebron, Berlakukan Jam Malam bagi Warga Palestina
PNC menyatakan bahwa praktik teroris Israel, termasuk rencananya untuk menganeksasi bagian dari Tepi Barat, mencerminkan kejahatan pemerintah Israel untuk terus menduduki tanah dan negara Palestina, dan menyeret kawasan itu ke eskalasi lebih lanjut.

Aneksasi Tepi Barat
Peringatan Hari Naksa 5 Juni 2020 – 5 Juni 1967 hendak mengingatkan para pejuang Palestina dan dunia Islam bahwa pendudukan Israel yang terus-menerus atas tanah-tanah Arab sedang menuju aneksasi tanah-tanah besar di Tepi Barat.
Baca Juga: Faksi-Faksi Palestina Diskusikan Strategi Perlawanan Terpadu
Dampak perang itu hingga kini masih berlanjut, karena Israel terus menduduki Palestina. Meskipun ada resolusi-resolusi internasional yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB, menuntut agar Israel menarik diri darinya. Israel tak bergeming untuk terus becokol di tanah jajahannya.
Tren Israel di bawah kesepakatan pemerintahan koalisi Netanyahu -Gantz berusaha mencaplok wilayah-wilayah besar lainnya di Tepi Barat, yang akan dimulai bulan Juli depan. Ini semua merupakan follow up dari draft Kesepakatan Abad Ini yang diajukan Presiden AS Donald Trump.
Trump menandatangani resolusi pengakuani Amerika Serikat bahwa Dataran Tinggi Golan adalah bagian dari Israel, yang ditolak oleh semua negara Arab dan sebagian besar anggota PBB.
Sebelumnya pada tahun 1993 ditandatangani Perjanjian Perdamaian Oslo antara Organisasi Pembebasan Palestina dan Israel yang menyepakati pembentukan Otoritas Palestina, dengan mensyaratkan penerapan sistem pemerintahan sendiri di tanah-tanah tersebut.
Baca Juga: Dua Tahun Genosida Israel Tidak Halangi Prestasi Siswa Gaza
Janjinya, negara Palestina yang merdeka akan didirikan, di samping Israel, setelah berakhirnya periode transisi pada tahun 1999, dan mengakhiri pendudukan Tepi Barat dan Gaza.
Namun buktinya, setelah kini 21 tahun sejak penandatanganan perjanjian di Oslo, Norwegia tanggal 20 Agustus 1999, ternyata Israel telah melepaskan kewajibannya, dan sebaliknya justru memaksakan pengadaan pemukiman-pemukiman Yahudi di Tepi Barat.
Penandatanganan perjanjian dilakukan oleh PM Israel Yitzak Rabin dan Ketua PLO Yasser Arafatyang disaksikan oleh Warren Christopher (AS) dan Andrei Kozyrev (Rusia) di depan Presiden AS Bill Clinton, , Ternyata terhenti oleh perilaku Israel sendiri, dan negosiasi politik pun terhenti.
Ambisi Israel malah semakin meningkat pada saat ini untuk mencaplok lebih banyak tanah Palestina, dengan menargetkan sekitar 30 persen dari wilayah Tepi Barat.
Baca Juga: Lembaga Kemanusiaan UNRWA Peringatkan Krisis Dana Serius
Menurut laporan Anadolu Agency pada Jumat (5/6/2020), Israel kini telah menguasai 85 persen wilayah Palestina, yang berjumlah sekitar 27 ribu kilometer persegi, dan terus menjarah komponen-komponennya. Sementara Palestina hanya memiliki sekitar 15 persen, dan itupun tunduk pada kekuasaan pendudukan Israel.
Sebuah perilaku yang digambarkan oleh pengamat hukum, sebagai “pelanggaran yang jelas dan eksplisit atas legitimasi internasional.”
Dalam pengamatan jurnalis dan intelektual Palestina di pengasingan, Dr Ahmed Frassini, mengatakan bahwa Palestina tidak memperoleh apapun dari Perjanjian Oslo yang ditandatangani bersama Israel.
“Kami tahu bahwa negosiasi dengan Israel tidak akan pernah memberi kami tanah kami. Kita tak punya pilihan selain berjuang untuk kemerdekaan,” kata Frassini.
Baca Juga: Hujan Lebat Landa Gaza, Tenda Pengungsi Hingga Rumah Sakit Kebanjiran
Dia mengungkapkan pandangan ini ketika mendiskusikan situasi terkini di Palestina bersama Geo TV di Brussels Ahad (24/5/2020) dalam tema memperingati Hari Al-Quds.
palestina-tak-peroleh-apa-pun-dari-perjanjian-oslo/">https://minanews.net/dr-frassini-palestina-tak-peroleh-apa-pun-dari-perjanjian-oslo/

Perjanjian Oslo
Baca Juga: Menakjubkan, Gen Z Gaza Melawan Genosida dengan Prestasi
Alih-alih gagalnya perwujudan Perjanjian Oslo, Komite Eksekutif PLO (Palestine Liberalization Organization) menegaskan siap untuk membatalkan semua perjanjian dengan Israel jika Israel masih tetap melaksana rencana aneksasi ke Tepi Barat, Wafa News Agency melaporkan, Sabtu (9/5/2020).
Komite PLO mengkonfirmasi, jika pemerintah Israel mencaplok bagian mana pun dari Tepi Barat, ia akan segera mengimplementasikan keputusan Dewan Nasional dan Pusat untuk membatalkan semua perjanjian dengan Israel.
Faksi PLO memimpin otoritas Palestina saat ini yang berpusat di Ramallah. PLO didirikan oleh tokoh perjuangan legendaris Palestina, Yasser Arafat, yang dulu menandatangani Perjanjian Oslo dengan Israel.
Pernyataan PLO itu dikeluarkan dalam pertemuan yang dipimpin PLO, Otoritas Palestina dan Presiden Fatah Mahmoud Abbas di Ramallah.
Dalam pertemuan itu, Abbas menekankan pesan “serius dan tegas” kepada masyarakat internasional.
https://minanews.net/plo-siap-batalkan-semua-perjanjian-dengan-israel/
Ancaman Mahmoud Abbas itu sendiri bukan yang pertama. Sebelumnya pada tahun 2015 Abbas menyampaikan pada pidato di sidang Majelis Umum PBB, Rabu (30/9/2015), yang menyebutkan bahwa Perjanjian Oslo sudah tidak relevan lagi karena Israel terus-menerus melanggar kesepakatan itu.
Dalam pidatonya, Abbas mengatakan Israel sebagai satu pihak penandatangan Perjanjian Oslo tetap bertindak sebagai negara penjajah yang menduduki Palestina, dengan terus membangun permukiman Yahudi di Tepi Barat dan tindakan agresif militer Israel terhadap warga Palestina.
Namun jika ancaman pembatalan Oslo itu terlaksana, akan berkonsekensi pada beberapa hal krusial bagi Palestina itu sendiri.
Ini seperti analisis Dr. Omar Shaban, Direktur PalThink for Strategic Studies berbasis di Gaza, sebuah lembaga think tank independen tanpa afiliasi politik.
Menurutnya, pembatalan Perjanjian Oslo akan secara efektif menghapus justifikasi hukum untuk Otoritas Palestina (PA). Ini akan berarti pembubaran Otoritas Palestina, pemberhentian staf dan karyawannya, mengakhiri pendanaan internasional, dan membatalkan perjanjian ekonomi antara PA dan Israel, serta antara PA dengan banyak negara lain di dunia.
Ini juga berarti berakhirnya koordinasi keamanan antara Israel dan PA, yang akan memfasilitasi kembalinya militer Israel ke bagian Tepi Barat yang ditunjuk sebagai Area A.
Menurut pendiri Komunitas Palestina untuk Amnesty International itu, mengakhiri Perjanjian Oslo akan menyebabkan eksodus perwakilan diplomatik asing dari Ramallah, serta membekukan semua proyek ekonomi bersama antara sektor swasta Palestina dan Israel di bidang energi, semen, listrik, telekomunikasi, dan lainnya, mengakibatkan kerugian ekonomi setidaknya ratusan juta dolar.
“Harga pembatalan Kesepakatan Oslo akan jauh lebih besar yang akan ditanggung oleh Otoritas Palestina dan masyarakat Palestina,” ujarnya.
Negosiasi Ulang
Dalam negosiasi terakhir, draft Kesepakatan Abad Ini mendorong Palestina menolak peran Amerika Serikat sebagai juru damai konflik dengan Israel.
Namun lagi-lagi, kekuatan besar AS membuat Palestina terdampak sendiri dengan renggangnya hubungan diplomatik tersebut.
Hubungan AS-Palestina kini telah mencapai titik terendah sepanjang sejarah. Kedua belah pihak belum bertemu sejak pemerintah AS mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel pada Desember 2017. Ketegangan semakin merebak ketika pemerintah AS terus merangkul posisi pemerintah sayap kanan Israel dan restu untuk menganeksasi sebagian wilayah Tepi Barat.
Menurut analisis Carmiel Arbit, peneliti tentang hubungan AS-Israel, di antara dampak yang paling meresahkan, bagaimanapun adalah penangguhan bantuan bersejarah AS untuk Palestina. Tidak peduli seberapa lama perdamaian itu tercapai, jika solusi dua negara yang dinegosiasikan AS dapat dilakukan, rakyat Palestina akan membutuhkan dukungan nyata AS.
Menurut Arbit yang juga pernah menjabat Direktur Strategis di Komite Urusan Publik Israel-Amerika Serikat, secara historis, AS telah menjadi negara donor terbesar bagi Palestina, meskipun dukungannya tidak tanpa kontroversi atau kekecewaan.
“Meskipun pendanaan gagal memberikan perdamaian yang awalnya dicari, itu masih menguntungkan semua pihak. Dengan bantuan dolar AS, Palestina mampu membangun perangkat awal sebuah negara, termasuk pemerintahan yang stabil, dan infrastruktur,” ujar Carmiel Arbit, seperti dimuat pada laman Atlantic Council, edisi 23 Desember 2019.
Palestina bulan-bulan terakhir merasakan krisis makanan, air dan kesehatan, yang bisa memperburuk ketidakstabilan. Ini disebabkan dicabutnya bantuan AS melalui Badan Bantuan PBB (UNRWA) yang secara signifikan biasanya digunakan untuk layanan sosial Palestina.
Pada akhirnya, jika solusi dua negara (two states solution) masih menjadi solusi yang paling realistis, tentu akan lebih menekan ketegangan dan konflik di lapangan, jika kembali ke pertemuan antara para pihak, baik Palestina, Israel dan Amerika Serikat, serta pihak keempat PBB.
Untuk keseimbangan diplomasi, negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan Palestina di luar sekutu AS perlu dilibatkan, mengingat ini sudah menjadi masalah internasional. Peluang terbesarnya ada pada Rusia, Turki atau Arab Saudi.
Catatan khusus untuk Arab Saudi, kekayaan minyak besar kerajaan dan perannya sebagai penjaga situs-situs paling suci Islam dan kiblat pemimpin de facto komunitas Muslim dunia menempatkannya dalam posisi kepemimpinan yang unik.
Dengan demikian, mengutip pandangan Prof Gawdat Bahgat, guru besar bidang keamanan nasional di Pusat Studi Strategis Timur Dekat Asia Tenggara, Universitas Pertahanan Nasional, Washington, DC. Ia mengat6akan, Saudi Peace Initiative sebenarnya semakin dipandang sebagai dasar untuk negosiasi negara-negara Arab-Israel, dan tentu didukung oleh Amerika Serikat, mitra kuat Arab Saudi.
Sebuah editorial di surat kabar Israel Haaretz seperti disebutkan Middle East Polidy Council (MEPC) menyatakan, “Hanya Arab Saudi yang dapat memberikan pengakuan dan legitimasi regional Israel, dengan imbalan penarikannya dari wilayah.” (A/RS2/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)















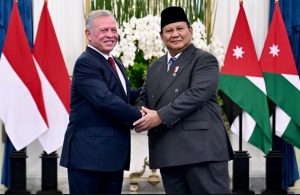



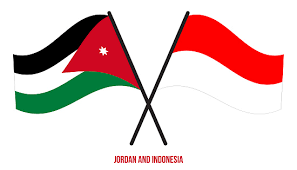














 Mina Indonesia
Mina Indonesia Mina Arabic
Mina Arabic Mina Preneur
Mina Preneur