FENOMENA Muslim Abangan di negeri ini bukanlah hal baru. Ia sudah lama mengakar, bahkan sebelum kata “Islam moderat” atau “Islam kaffah” ramai diperbincangkan. Muslim abangan biasanya dikenal sebagai mereka yang mengaku Islam, namun lebih dekat kepada adat, budaya, dan tradisi turun-temurun ketimbang kepada syariat Islam itu sendiri. Mereka menjalani hidup dengan identitas Islam, tetapi nilai-nilai Islam sering kali tertutupi oleh kabut tradisi yang dianggap sakral.
Fenomena ini menyentuh hati karena sejatinya banyak dari mereka yang berbuat demikian bukan karena benci agama, melainkan karena ketidaktahuan. Islam dipandang hanya sebatas nama di KTP, atau sebatas warisan keluarga, tanpa disertai pemahaman mendalam tentang kewajiban sebagai hamba Allah. Akhirnya, budaya yang diwarisi dari leluhur menjadi kompas utama, sementara Al-Qur’an dan Sunnah justru dibiarkan terpinggirkan.
Cinta budaya adalah sesuatu yang wajar. Islam pun tidak melarang umatnya menjaga tradisi selama tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat. Namun yang menyedihkan adalah ketika cinta budaya melampaui cinta kepada agama. Banyak yang rela mengeluarkan biaya besar untuk pesta adat, tetapi enggan mengeluarkan sedikit harta untuk membangun masjid, membantu yatim, atau menunaikan zakat. Inilah titik rawan di mana budaya menenggelamkan syariat.
Lupa syariat bukanlah persoalan kecil. Shalat yang lima waktu ditinggalkan, puasa dianggap beban, jilbab hanya simbol tanpa makna, sementara acara-acara adat yang berbalut syirik justru dijalani dengan penuh semangat. Bagaimana mungkin seorang Muslim meremehkan perintah Allah, tetapi begitu takut melanggar adat yang dibuat manusia? Bukankah ini adalah kebalikan dari fitrah yang seharusnya?
Baca Juga: Kritik Radikal Ilan Pappe terhadap Proyek Kolonial Israel
Fenomena Muslim abangan menyentak alam bawah sadar kita: benarkah kita sudah benar-benar Muslim sejati, atau jangan-jangan kita hanya berlabel Muslim, tetapi lebih mengabdi pada warisan leluhur daripada Rabb semesta alam? Pertanyaan ini penting untuk direnungkan, karena Al-Qur’an menegaskan: “Masuklah kamu ke dalam Islam secara kaffah” (QS. Al-Baqarah: 208). Islam tidak menerima setengah hati, apalagi hanya sebatas nama.
Kita harus jujur pada diri sendiri. Jika kita mencintai budaya lebih daripada syariat, maka sebenarnya kita sedang menjadikan budaya sebagai “tuhan kecil” dalam hidup kita. Padahal Allah berfirman, “Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan mereka?” (QS. Al-Furqan: 43). Bukankah lebih mengerikan jika budaya yang seharusnya menjadi identitas sosial justru menyeret kita ke jurang kesyirikan?
Budaya bisa menjadi indah jika ia dipoles dengan cahaya Islam. Namun budaya juga bisa menjadi racun jika ia dibiarkan menggerogoti akidah. Muslim sejati adalah mereka yang menimbang budaya dengan neraca syariat. Jika sesuai, ia dipertahankan. Jika bertentangan, ia ditinggalkan. Itulah keseimbangan yang diajarkan Islam: menghargai tradisi, tetapi tetap meletakkan syariat sebagai mahkota.
Fenomena Muslim abangan sering kali diwariskan lintas generasi. Anak-anak tumbuh melihat orang tua yang lebih sibuk mengurus selamatan, pesta panen, atau tradisi lain, sementara shalat jamaah di masjid justru sepi. Anak-anak ini akhirnya belajar bahwa agama hanyalah “formalitas”, bukan pegangan hidup. Maka, lahirlah generasi yang mengenal adat lebih dekat daripada mengenal Allah dan Rasul-Nya.
Baca Juga: Pentingnya Narasi dan Literasi dalam Perjuangan Palestina
Namun harapan selalu ada. Banyak Muslim abangan yang kemudian menemukan hidayah setelah belajar Islam lebih dalam. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka keliru dalam memposisikan budaya. Mereka menemukan kebahagiaan sejati dalam shalat, ketenangan dalam tilawah, dan kehormatan dalam menegakkan syariat. Dari sinilah lahir generasi Muslim baru yang tetap mencintai budaya, tetapi lebih mencintai Allah.
Kita yang membaca fenomena ini tidak boleh berhenti hanya pada kritik. Kita harus menjadi bagian dari solusi. Jangan biarkan Muslim abangan merasa dijauhi. Sebaliknya, kita dekati dengan kasih sayang, kita ajak dengan hikmah, kita ingatkan dengan keteladanan. Rasulullah ﷺ pun tidak pernah mencela kaumnya yang jahil, melainkan membimbing mereka dengan sabar hingga mereka menjadi sahabat-sahabat terbaik dalam sejarah.
Setiap kita bisa jadi pernah berada dalam lingkaran Muslim abangan. Mungkin kita masih mencintai tradisi lebih daripada syariat. Mungkin kita masih sibuk dengan adat tanpa peduli kepada Al-Qur’an. Namun hari ini bisa menjadi titik balik. Allah selalu membuka pintu taubat bagi hamba-hamba-Nya yang ingin kembali. Tidak ada kata terlambat untuk meninggalkan “Islam KTP” dan masuk ke dalam Islam yang kaffah.
Bayangkan jika budaya kita yang kaya raya itu dipoles dengan nilai-nilai Islam. Pesta adat diganti dengan syukuran sederhana yang penuh doa. Lagu daerah dihidupkan dengan lirik Islami. Kearifan lokal dijadikan sarana dakwah. Betapa indah wajah Nusantara jika Islam dijadikan ruh yang menghidupkan setiap tradisinya. Itulah cita-cita yang seharusnya kita perjuangkan.
Baca Juga: Ternyata Jadi Ayah Tak Seindah Cerita Film
Fenomena Muslim abangan adalah alarm keras bagi umat Islam. Ia adalah pengingat bahwa kita bisa kehilangan identitas sejati jika tidak hati-hati. Cinta budaya itu indah, tetapi jangan sampai membuat kita lupa pada syariat. Sebab, budaya hanya menyelamatkan kita di mata manusia, sedangkan syariatlah yang menyelamatkan kita di hadapan Allah.
Maka, mari kita bertanya lagi pada diri sendiri: maukah kita terus menjadi Muslim abangan, atau kita siap naik kelas menjadi Muslim sejati? Pilihan itu ada di tangan kita. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan hanya pada adat tanpa ibadah. Jalan kembali kepada Allah selalu terbuka. Tinggal kita yang berani melangkah.
Dan saat kita memilih jalan Islam yang kaffah, saat itulah budaya dan syariat tidak lagi bertentangan, melainkan berjalan beriringan. Budaya menjadi sarana dakwah, syariat menjadi ruh kehidupan. Inilah wajah Islam yang sesungguhnya—agama yang menuntun manusia menuju keselamatan dunia dan akhirat.[]
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Abraham Accords Membidik Arab Saudi dan Indonesia, Mungkinkah?
















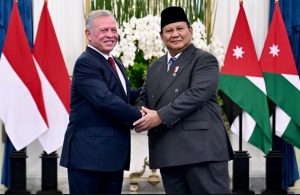

















 Mina Indonesia
Mina Indonesia Mina Arabic
Mina Arabic Mina Preneur
Mina Preneur