Oleh Annisa Salsabila, Mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
ENAM tahun telah berlalu sejak pandemi mengurung manusia dalam ruang-ruang digital. Kala itu, dunia nyata seolah membeku, sementara dunia maya menjadi tempat semua hal terjadi: belajar, bermain, bahkan berinteraksi. Anak-anak, yang semestinya tumbuh dengan tawa dan percakapan langsung, justru berkenalan dengan layar lebih dulu daripada teman sebaya.
Di balik rasa aman karena “anak di rumah saja”, banyak orang tua tak sadar bahwa isolasi sosial itu menanam benih baru: anak-anak yang kehilangan kemampuan berinteraksi dan berekspresi secara sehat. Ketika pandemi usai, kebiasaan digital itu tetap melekat. Gawai bukan lagi sekadar alat bantu, tapi telah menjelma teman, guru, sekaligus “pengganti” orang tua dan dunia nyata.
Akibatnya, muncul generasi yang fasih berselancar di dunia maya, tapi gagap dalam bertutur di dunia nyata. Bahasa yang seharusnya menjadi cermin pikiran dan karakter, kini berubah menjadi alat ekspresi tanpa etika.
Baca Juga: Ketika Baitul Maqdis Mengajarkan Iman dan Akhlak kepada Para Pelajar
Ketika Bahasa Kasar Jadi Tren
Fenomena bahasa kasar di kalangan anak-anak Gen Z (dan sekarang juga Gen Alpha) memang sedang jadi sorotan para pendidik, psikolog, dan peneliti bahasa. Banyak studi menunjukkan bahwa media sosial, terutama TikTok, YouTube Shorts, dan game online, berperan besar dalam membentuk pola tutur anak-anak saat ini.
Menurut penelitian Lingua: Jurnal Bahasa dan Sastra (2023) serta laporan Kominfo dan UNICEF (2022), beberapa bentuk bahasa kasar yang kini sering digunakan anak-anak seperti kata umpatan ringan: “anjir”, “anjay”, “gila”, “bodoh”, “tolol”, dan “kampret”.
Selain itu, jenis kata ejekan atau hinaan fisik seperti, “gendut”, “jelek”, “hitam”, “cupu”, “alay” dan kata sarkas ujaran marah misalnya, “ngapain sih lo?”, “bodo amat”, “dasar bego”, dan “diam lu!”.
Baca Juga: Saat Sekolah Jadi “Pabrik” Kebobrokan Akhlak
Penggunaan kata-kata kasar dan sikap semena-mena di kalangan anak-anak kini makin mencolok. Ironisnya, perilaku itu justru banyak ditemukan pada usia sekolah dasar, masa di mana karakter dan moral sedang dibentuk. Bahasa yang dulu tabu diucapkan kini terdengar lumrah di halaman sekolah, di rumah, bahkan dalam konten media sosial yang mereka tonton setiap hari.
Sebagian anak menganggap kata kasar bukanlah kesalahan, melainkan cara menegaskan diri. “Biar kelihatan berani,” begitu alasannya. Bahasa bagi mereka bukan lagi alat komunikasi, tapi simbol eksistensi.
Padahal, di balik “keberanian” itu, ada krisis yang lebih dalam, krisis empati dan keteladanan.
Keteladanan yang Hilang
Baca Juga: Urgensi Kegiatan Jurnalistik bagi Pelajar
Hasil survei sederhana terhadap orang tua, guru, dan pengamat sosial menunjukkan 90% responden melihat perubahan mencolok pada cara anak berinteraksi. Bahasa mereka dinilai semakin keras, spontan, dan tak lagi mempertimbangkan kesopanan. Sekitar 70% meyakini bahwa media digital dan lingkungan pertemanan menjadi faktor utama, ditambah lemahnya pengawasan dan contoh dari orang dewasa.
“Pergaulan dan media sosial tidak akan berpengaruh besar jika anak mendapat pendidikan moral yang baik sejak dini,” ungkap salah satu responden. Pandangan ini sejalan dengan konsep learning by example, bahwa anak-anak belajar bukan dari kata-kata, tapi dari perilaku orang tuanya.
Sayangnya, banyak anak justru melihat contoh sebaliknya. “Ibu guru suka marah-marah kalau kami salah. Mama juga begitu di rumah,” kata seorang anak polos. Kalimat sederhana ini menjadi cermin yang menohok: anak-anak meniru bukan karena diajari, tapi karena terbiasa melihat.
Bahasa Adalah Cermin Peradaban
Baca Juga: Pendidikan Prenatal dalam Al-Qur’an, Refleksi dari Kisah Keluarga Imran
Bahasa adalah wajah pertama seseorang. Dari tutur kata, orang lain menilai kepribadian dan latar nilai seseorang. Ketika bahasa kehilangan sopan santun, maka rusak pula struktur sosial yang menopangnya.
Fenomena ini menunjukkan bahwa krisis bahasa di kalangan anak bukan masalah spontanitas, tetapi sinyal menurunnya fungsi pengawasan, keteladanan, dan kedekatan emosional antara anak dan lingkungannya.
Mendidik dengan Contoh, Bukan Sekadar Kata
Menumbuhkan kembali sopan santun pada anak tidak bisa dilakukan dengan ceramah atau larangan semata. Diperlukan keteladanan nyata, orang tua yang sabar, guru yang mendidik dengan kasih, dan lingkungan yang menumbuhkan empati.
Baca Juga: Wamenag Ajak Pengusaha Bersinergi dengan Pesantren
Sebagian besar responden dalam penelitian ini menyarankan tiga pendekatan utama:
Pendidikan karakter sejak dini melalui pembiasaan bahasa sopan dalam percakapan harian.
Keteladanan orang dewasa, terutama di rumah dan sekolah, agar anak belajar dari perilaku, bukan perintah.
Pendekatan moral dan spiritual, agar anak memahami makna ucapan, bukan sekadar bentuknya.
Baca Juga: Ketika Ilmu Tak Lagi Mendidik: Potret Gelap Pendidikan di Akhir Zaman
Sebagian lainnya menilai bahwa hukuman mendidik, seperti meminta maaf setelah menyakiti teman, bisa menjadi pelajaran berharga. Bagi anak, meminta maaf bukan hal kecil, melainkan proses belajar mengenali salah dan bertanggung jawab.
Anak Bukan Pelaku, Tapi Cerminan Lingkungan
Pada akhirnya, anak-anak bukanlah pihak yang harus disalahkan. Mereka hanyalah cermin dari dunia yang membentuknya. Bahasa kasar yang mereka ucapkan adalah gema dari cara orang dewasa berbicara di rumah, di media sosial, atau bahkan di sekolah.
Maka, jika kita ingin anak-anak tumbuh menjadi generasi yang santun dan berempati, perbaikilah lingkungan yang mengitarinya. Ajarkan mereka cara mengekspresikan diri dengan bijak, dan tunjukkan bahwa keberanian sejati bukan diukur dari kerasnya suara, tapi dari lembutnya hati.
Baca Juga: Meneguhkan Peran Santri di Era Digital
Bahasa yang sopan adalah awal dari peradaban yang beradab. Dan tugas menjaga peradaban itu, bukan hanya milik anak-anak, tapi tanggung jawab kita semua. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Teknologi Bisa Mengajar, Tapi tak Mampu Membentuk Karakter
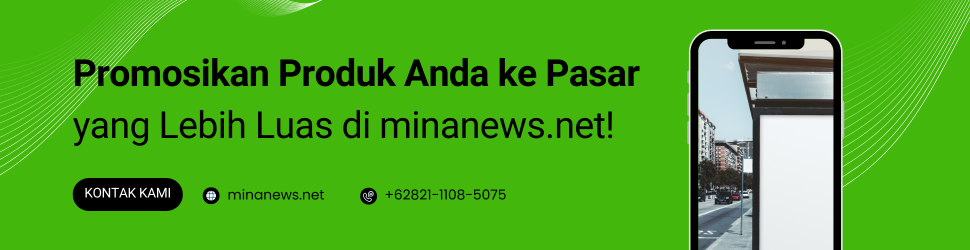





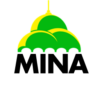


















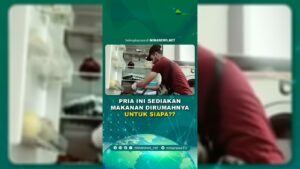



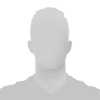
 Mina Indonesia
Mina Indonesia Mina Arabic
Mina Arabic Mina Preneur
Mina Preneur