Pondok Pesantren Al-Fatah yang terletak di Pasirangin, Cileungsi, Bogor, memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan kontribusi para pendirinya. Sejak berdiri pada tahun 1980, sejumlah tokoh perintis seperti Bustamin Utje, Aji Muslim, Toha, Ruslani, Ta’rif, Sirajuddin Arsyad, dan Saifuddin Adjukarsa telah membangun fondasi yang kuat bagi perkembangan pesantren ini.
Salah satu figur penting dalam sejarah perjalanan Pondok Pesantren Al-Fatah adalah Abdul Qohar, yang lebih dikenal sebagai Abah Qohar. Bersama istrinya, Sulastrih, ia hijrah ke Cileungsi pada sekitar tahun 1982 dari Lampung dan bergabung dengan gelombang hijrah lainnya untuk menghidupkan pesantren.
Sebelumnya, Bustamin Utje dan beberapa orang dari Tanjung Priok, Jakarta Utara, telah mendapat amanah dari Imaam Muhyidin Hamidy untuk membeli tanah di Pasirangin, yang kala itu masih berupa hutan bambu. Proses pembelian tanah ini, yang dimulai pada Agustus 1980, menjadi langkah awal berdirinya Pondok Pesantren Al-Fatah.
Pada era 1980-an, Pasirangin dianggap sebagai daerah angker, dan banyak orang enggan memasukinya. Namun, berkat upaya Abah Qohar dan rekan-rekannya, persepsi ini berubah. Lahan yang dulunya sulit dijual berhasil dibeli untuk pembangunan pesantren dengan harga 500 rupiah per meter saat itu.
Baca Juga: Terpilih Lagi jadi Ketua MUI, Ini Profil Lengkap KH Anwar Iskandar
Kehadiran Abah Qohar di Pasirangin bukan hanya untuk membantu mendirikan pesantren, tetapi juga untuk menghadapi praktik tahayul dan kemusyrikan yang masih kuat di masyarakat. Dengan semangat yang teguh, Abah Qohar dan para asatidz lainnya berupaya memperkenalkan kembali ajaran Islam yang sesuai dengan sunnah.
Dari Banjaran ke Talang Padang
Abdul Qohar lahir di Banjaran, Pameungpeuk, Bandung, Jawa Barat, pada tahun 1943, di masa-masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Masa kecilnya penuh dengan tantangan, termasuk ketika keluarganya harus mengungsi ke gua untuk menghindari bahaya akibat Agresi Militer Belanda yang kedua. Ayahnya, Encung, dan ibunya, Enong, membawa Qohar ke tempat yang aman di tengah situasi yang tidak menentu.
“Menurut bapak saya, saat Agresi Militer Belanda yang kedua, kami sekeluarga mengungsi mencari perlindungan di gua. Kehidupan sangat sulit waktu itu, dan saya ikut dibawa mengungsi,” ujar Qohar mengisahkan masa kecilnya di Bandung.
Baca Juga: Sheikh Hasina, Dari Dominasi Politik ke Vonis Hukuman Mati
Ketika gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) berlangsung, keluarganya juga harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang penuh ketidakpastian.
“Saya diasuh oleh orang-orang DI/TII, jadi situasinya serba salah. Kami juga dekat dengan tentara. Karena kami sama-sama tinggal di kampung,” tambahnya.
Pada tahun 1958, Abah Qohar dan keluarganya pindah ke Lampung untuk menghindari konflik yang melibatkan gerakan DI/TII. Mereka memulai kehidupan baru di Talang Padang. Selama di sana, Abah Qohar dan keluarganya menghadapi tekanan dari gerombolan Partai Komunis Indonesia (PKI), terutama karena keteguhan mereka dalam menjalankan ajaran Islam.
“Karena bapak saya termasuk keluarga yang taat beribadah dan berusaha menjalankan sunnah, kami menjadi target PKI. Mereka tidak suka dengan orang yang taat beragama,” jelas Qohar.
Baca Juga: Zohran Mamdani, Jejak Anak Imigran Muslim Merebut Panggung Amerika
Pada tahun 1965, Abah Qohar pertama kali bertemu dengan Ustaz Saifuddin Adjukarsa di Pringsewu, Lampung. Pertemuan ini menjadi titik awal keterlibatan aktif Abah Qohar dalam dakwah sunnah yang mendorong persatuan umat Islam dan kehidupan berjamaah. Pertemuan tersebut memperkuat semangat Qohar dan keluarganya untuk semakin teguh dalam jalan dakwah.
“Dulu, kami jarang membahas hal-hal duniawi seperti bisnis atau kehidupan sehari-hari. Obrolan kami lebih sering berkisar tentang agama, perjuangan, dan dakwah ketika bertemu dengan ikhwan-ikhwan,” katanya.
Qohar mengakui bahwa ketertarikannya pada dakwah awalnya disebabkan oleh keterlibatan orang tuanya yang sering aktif bersama Ustaz Saifuddin. Sebagai pemuda yang masih labil, ia belum sepenuhnya terlibat dalam dakwah, terlebih saat itu gerakan Komando Jihad (Komji) sedang marak di Lampung, sehingga keluarganya kerap dituduh sebagai anggota Komji.
Abah Qohar juga menjadi saksi hidup dan peserta dalam acara Musyawarah Alim Ulama dan Zuama yang diadakan oleh Jama’ah Muslimin (Hizbullah) pada 25-27 Jumadil Awal 1394 H (15-17 Juni 1974 M) di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta, yang bertujuan menyatukan kaum muslimin.
Baca Juga: Mengenal Sosok Hemedti Komandan RSF dan Sudan yang Terbelah
Masuk Penjara Karena Dituduh Terlibat Komji
Suatu ketika, Abah Qohar sempat kembali ke Banjaran, Bandung, setelah berada di Lampung. Di sana, ia mulai berdakwah dan memimpin sekelompok kecil, sebanyak 18 orang. Metodenya dalam berdakwah cukup unik. Meskipun tidak pandai berbicara di depan umum atau beretorika, ia hanya membawa buletin Al-Jamaah dan membagikannya kepada teman-teman lamanya.
Perubahan perilaku Qohar membuat banyak dari kawan-kawannya heran. Dahulu, ia dikenal sebagai pemuda yang sering berkelahi dan dianggap sebagai “jagoan” di Banjaran. Di sudut terpencil Banjaran, terjadi perubahan besar pada dirinya. Wajahnya yang dulu penuh amarah kini tampak tenang. Tangannya, yang dulu sering terkepal siap menghadapi siapa saja, kini membawa buletin Al-Jamaah, sebuah bacaan yang menjadi alat dakwahnya.
“Teman-teman yang dulu sering berkelahi bersama saya heran melihat perubahan ini,” kenangnya dengan senyum.
Baca Juga: Hassan al-Turabi Pemikir Kontroversial dari Sudan
Abah Qohar saat itu memiliki koleksi lengkap Risalah Al-Jamaah dari edisi 01 hingga 28, dan inilah yang menjadi modal dakwahnya, mengajak orang untuk mengikuti ajaran Sunnah.
“Mereka bilang, kok bisa berubah jadi lebih alim. Saya cuma menyuruh mereka membaca buletin Al-Jamaah yang saya letakkan di meja ruang tamu,” katanya.
Namun, perubahan ini tidak selalu diterima dengan baik. Ketika kembali ke Bandung, ia malah ditangkap dan dibawa ke Kodim, di mana ia ditahan selama sepuluh hari. Tuduhan yang diarahkan padanya adalah sebagai anggota Komando Jihad (Komji) yang tengah bergerilya di Bandung, tuduhan yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan.
Setelah itu, ia dipindahkan ke Polsek Cimahi di kawasan Cibabat. Di sana, ia bertemu dengan Ustaz Masturo dari Sukabumi. Salah satu anggota keluarganya yang juga seorang tentara berpangkat datang menjenguknya di penjara. Entah apa yang dibicarakan saudaranya dengan pihak kepolisian.
Baca Juga: Sunan Drajat: Dakwah Kasih Sayang yang Menyentuh Hati
“Salah tangkap ini,” ujar seorang polisi yang terdengar oleh Qohar dari balik sel.
“Orang ini makmum Wali Al-Fatah, bukan anggota Komji,” kata Abah Qohar, menirukan percakapan polisi saat itu.
Masa-masa sulit tersebut tidak mematahkan semangat Qohar. Seperti aliran sungai yang terus mengalir meskipun terhalang, ia tetap melanjutkan hidupnya. Pesantren Al-Fatah di Cileungsi menjadi tempat di mana ia menumpahkan segala harapan dan usahanya.
Hidup di Cileungsi tidak selalu berjalan mudah. Saat kebutuhan hidup semakin mendesak, Qohar sering pergi ke Pasar Cileungsi, menjual koran bekas untuk mendapatkan uang guna membeli sayuran yang kemudian dibagikan kepada ikhwan yang baru datang ke Cileungsi.
Baca Juga: Tiga Ulama, Satu Napas Keilmuan Pesantren Lirboyo
“Kami dulu banyak disantuni oleh Imaam dan ikhwan dari Tanjung Priok, Petojo, Jakarta,” ungkapnya. “Makanan kami dijatah, karena semua di sini berusaha melakukan amal shaleh dengan membantu pembangunan dan kegiatan pondok.”
Meskipun demikian, Qohar adalah orang yang tidak suka bergantung pada orang lain. Ia sering kembali ke pasar, kadang hanya untuk mengambil sisa sayuran yang sudah layu tapi masih bisa dimakan, atau menjual koran bekas untuk membeli ikan asin. Seiring waktu, para pedagang pasar mulai mengenalinya sebagai orang dari pesantren dan sering memberinya sayuran yang sudah tidak segar tetapi masih layak dimasak.
“Orang-orang di pasar tahu kami berasal dari pesantren,” kenangnya.
“Akhirnya, sering diberi sayuran yang sudah agak layu,” ujarnya, mengenang masa lalu.
Baca Juga: Sunan Bonang, Sang Penuntun Jiwa yang Mengharmonikan Cahaya Islam dan Budaya Nusantara
Abah Qohar masih ingat datangnya gelombang orang-orang yang berhijrah ke Pesantren, meskipun tidak bisa mengingat tahun pastinya, ia dapat merinci kedatangan orang-orang yang menambah suasana hidup di Al-Fatah.
Di antara generasi awal yang datang ke Cileungsi, sekitar tahun 1980, ia mengingat Ustaz Aji Muslim, Ustaz Sirajuddin, dan Ustaz Ta’rif. Kemudian, pada tahun berikutnya, datang Ustaz Abdul Hanan dan almarhum Aliyuddin Nuzlan Nasution, serta Ustaz Qomaruddin Basuni.
Rombongan pengungsi dari letusan Gunung Galunggung di Tasikmalaya juga tiba, termasuk almarhum Pak Muwahid, Ustaz Abul Bana, dan Ustaz Muhajir Al Murtaqi.
Pada tahun-tahun berikutnya, sekitar 1983, datang Ridwansyah, Abdurrahman RT, Ustaz Abul Hidayat, dan Saifuddin, yang menetap di Lampung tetapi lebih sering berdakwah di Cileungsi. Kemudian pada tahun 1985, datang Ustaz Shobaruddin bersama rombongan dari Tanjung Priok, termasuk Samsuri, Tasmo, dan Durrohim.
Baca Juga: Prof. Omar Yaghi, Seorang Pengungsi Palestina yang Menangkan Hadiah Nobel Bidang Kimia
Di balik penampilannya yang sederhana, Qohar memiliki tekad yang kuat. Perjalanan hidupnya, dari seorang jagoan jalanan hingga menjadi penyebar cahaya ilmu, merupakan kisah tentang transformasi, perjuangan, dan pengabdian yang tak kenal lelah.
Terlepas dari berbagai tantangan, ia terus maju, meninggalkan warisan keberanian dan keteguhan hati bagi generasi penerusnya. Abah Qohar memiliki tujuh anak, yaitu Qomaruddin, Watikah, Amrullah, Lilis Rodliyah, Muadz, Mikdad, dan Ruwaidah.
Anak-anak ini, yang ia besarkan bersama istrinya, Sulastrih, yang kini telah berpulang, menjadi saksi di Pasirangin, sebuah tempat yang kini terus berkembang seiring dengan perubahan Cileungsi menuju kota metropolitan.[Arif R]
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Sunan Ampel, Pelita Peradaban Islam di Tanah Jawa






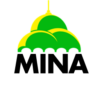























 Mina Indonesia
Mina Indonesia Mina Arabic
Mina Arabic Mina Preneur
Mina Preneur