Oleh Lili Ahmad, Manajer MINA Publishing House
Kesabaran, sebagai sebuah kata memang terdengar begitu sederhana, tetapi secara makna ia menyimpan kedalaman yang hanya mampu diselami oleh mereka yang memiliki keberanian untuk menelusuri labirin kehidupan. Bagi kesabaran, waktu bukan hanya sekadar hitungan menit yang berlalu, melainkan sebuah ruang yang membuat jiwa terus berjuang, menanti, dan menemukan makna. Eksistensialisme memungkinkan kita untuk meminjam lensanya yang jernih sebagai alat untuk memahami hakikat kesabaran sebagai pengalaman yang mendasar bagi manusia.
Manusia dikutuk untuk bebas, begitu kata Jean-Paul Sartre. Kebebasan yang menempatkan manusia dalam situasi yang terus-menerus mengharuskannya membuat pilihan—pilihan yang terkadang menuntutnya untuk bersabar. Di dalam kehidupan yang dipenuhi oleh absurditas dan ketidakpastian, kesabaran tidak hanya sekadar menanti dengan pasrah, tetapi menanggung beban eksistensi dengan penuh keberanian. Seperti Sisyphus yang terus mendorong batu ke atas bukit tanpa akhir, manusia sering kali terjebak dalam rutinitas yang tampaknya sia-sia. Namun, tentu saja di dalam absurditas itu, ada laku yang terus diuji, dan kesabaran adalah upaya manusia untuk tetap berdiri tegak di dalam kebebasan memilih, walau pilihan itu tampak tak bermakna.
Sementara itu, Friedrich Nietzsche mengajarkan kita tentang pentingnya menjadi Übermensch—manusia unggul yang mampu melampaui batasan dirinya. Dalam konteks ini, kesabaran tidak dipandang sebagai kelemahan, melainkan kekuatan yang murni, yang tumbuh dari keberanian untuk menahan dan menunggu saat yang tepat. Nietzsche, dengan pandangan tragisnya terhadap kehidupan, memahami bahwa penderitaan adalah bagian tak terhindarkan dari eksistensi. Namun, di dalam penderitaan itulah, manusia menemukan potensi tertingginya. Kesabaran adalah penantian yang penuh kesadaran; ia menantang kita untuk melihat penderitaan sebagai bagian dari proses penciptaan diri.
Baca Juga: Dari Bandung untuk Al-Aqsa, Tabligh Akbar Menyatukan Umat dalam Ukhuwah dan Perjuangan
Kita juga bisa menelusuri jejak kesabaran dalam pemikiran Søren Kierkegaard, sang bapak eksistensialisme. Bagi Kierkegaard, kesabaran berkait erat dengan iman. Dalam karya monumentalnya, Fear and Trembling, dia menggambarkan kisah Ibrahim (Abraham dalam bahasanya) yang dengan sabar menanti perintah Tuhan, bahkan ketika dia dihadapkan pada pilihan yang paling sulit dalam hidupnya—mengorbankan anaknya, Ismail (Ishak dalam kepercayaannya). Bagi Kierkegaard, kesabaran adalah wujud kepercayaan pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Ini adalah bentuk keberanian tertinggi, saat kita menerima ketidakpastian dengan penuh kerendahan hati, tetapi tanpa kehilangan harapan.
Kesabaran, dalam bingkai eksistensialisme, bukanlah sesuatu yang pasif. Ia tidak sekadar diam dan menunggu. Sebaliknya, kesabaran adalah aksi. Ia adalah perjuangan batin yang terus-menerus, ketika kita berhadapan dengan absurditas, kebebasan, dan kehendak untuk menjadi. Kita menunggu, bukan karena terpaksa, melainkan karena kita memilih untuk menunggu—karena dalam penantian itu, kita menemukan makna yang lebih dalam dari keberadaan kita sendiri.
Bagi Camus, hidup adalah pemberontakan melawan absurditas. Kesabaran, dengan demikian, adalah bentuk pemberontakan paling halus dan paling tangguh. Ia menolak untuk tunduk pada keputusasaan, meskipun dunia tampak tak masuk akal. Camus mengajarkan kita bahwa hidup itu sendiri adalah perjuangan yang layak dijalani, meskipun tanpa jaminan makna yang pasti. Seperti tokoh Meursault dalam The Stranger, yang menghadapi dunia dengan kebisuan dan keterasingan, kita dituntut untuk bersabar dalam menghadapi absurditas yang tak terelakkan. Namun, bagi Camus, kesabaran ini bukanlah ketundukan pada nasib, melainkan bentuk dari perlawanan diam-diam terhadap kekosongan. Ia adalah keputusan untuk terus hidup, untuk terus berjuang, meski dunia tidak pernah memberi jawaban yang jelas.
Namun, jika filsafat eksistensialisme menyoroti kesabaran sebagai respons terhadap kebebasan dan absurditas, para filsuf Islam menawarkan perspektif yang lebih spiritual dan transenden.
Baca Juga: 5 Adab Mulia yang Harus Diketahui Peserta Tabligh Akbar
Imam Al-Ghazali, dalam karyanya yang monumental Ihya Ulumuddin, menggambarkan kesabaran (sabr) sebagai salah satu elemen utama dalam perjalanan spiritual manusia. Bagi Al-Ghazali, kesabaran adalah ketundukan penuh kepada kehendak Ilahi, yang mengajarkan manusia untuk menahan diri dari keinginan duniawi dan menjaga diri dari keburukan. Kesabaran menjadi landasan bagi seseorang untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Dia menggambarkan bahwa kesabaran itu ada dalam tiga bentuk: kesabaran dalam ketaatan, kesabaran dalam menghadapi cobaan, dan kesabaran dalam menahan nafsu. Dalam pandangan Al-Ghazali, kesabaran adalah bentuk penerimaan yang tidak pasif, tetapi aktif—menanti dengan keyakinan bahwa segala sesuatu adalah ujian dari Allah Subhanahu wata’ala untuk menguji keteguhan iman.
Ibnu Miskawaih, filsuf Islam yang dikenal dengan karyanya Tahzib al-Akhlaq, juga memandang kesabaran sebagai salah satu bentuk kebajikan moral tertinggi. Dalam etikanya, kesabaran adalah kemampuan untuk menahan diri dari dorongan emosional yang dapat merusak akal dan jiwa. Bagi Ibnu Miskawaih, kesabaran adalah proses pengendalian diri yang berkelanjutan, yang melibatkan keseimbangan antara akal dan hawa nafsu. Ini adalah bagian dari pencapaian kesempurnaan moral yang bertujuan membawa manusia menuju kebahagiaan sejati—sa‘ada—yang hanya bisa diraih melalui pengendalian diri yang penuh kesadaran.
Pandangan Muhammad Iqbal, seorang filsuf Islam modern, membawa kita pada pemahaman yang lebih progresif tentang kesabaran. Dalam karyanya The Reconstruction of Religious Thought in Islam, Iqbal melihat kesabaran sebagai kekuatan dinamis dalam kehidupan manusia. Bagi Iqbal, kesabaran bukanlah sekadar menanti dengan tenang, tetapi merupakan bentuk daya hidup yang memotivasi manusia untuk terus berjuang melampaui batasan-batasan yang ada. Kesabaran adalah manifestasi dari kehendak yang kuat untuk berkembang, untuk bertindak, dan untuk terus mencari kemajuan. Dalam pandangan Iqbal, kesabaran tidaklah statis, melainkan energi yang menggerakkan manusia menuju pencapaian tujuan-tujuan spiritual dan duniawi.
Dengan demikian, baik dalam pandangan eksistensialis maupun filsafat Islam, kesabaran memiliki makna yang dalam dan beragam. Dalam eksistensialisme, ia adalah perlawanan diam-diam terhadap absurditas dan ketidakpastian, sementara dalam filsafat Islam, ia adalah bentuk ketundukan yang aktif kepada kehendak Ilahi dan proses penyempurnaan diri. Namun, di balik perbedaan ini, ada benang merah yang menghubungkan keduanya—bahwa kesabaran adalah kekuatan yang memungkinkan manusia untuk menghadapi dunia dengan keberanian, harapan, dan keteguhan hati. Kesabaran adalah penopang eksistensi diri manusia yang paling niscaya.[]
Baca Juga: Zionis Manfaatkan Serangannya ke Iran untuk Tutup Masjid Al-Aqsa
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Mengapa Israel Nekat Menyerang Iran?






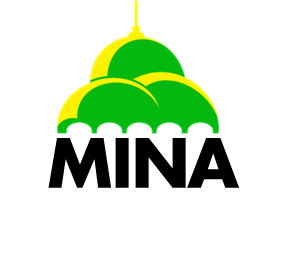































 Mina Indonesia
Mina Indonesia Mina Arabic
Mina Arabic Mina Preneur
Mina Preneur