HAJI bukan sekadar perjalanan fisik menuju tanah suci, melainkan perjalanan spiritual yang sarat makna dan penuh penghayatan. Ia adalah panggilan ilahi bagi mereka yang terpilih, untuk menapaki kembali jejak para nabi, dari Nabi Ibrahim, Ismail, hingga Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam. Dalam setiap langkah, dari thawaf hingga sa’i, dari wukuf hingga melempar jumrah, seorang Muslim sedang menjalani teater ruhani yang menghidupkan kembali semangat tauhid dan kepasrahan.
Ibadah haji adalah bentuk penghambaan total kepada Allah Ta’ala. Saat seorang hamba mengenakan ihram, ia melepaskan identitas duniawinya—status sosial, harta benda, dan perbedaan suku—lalu bersatu dalam kesetaraan di hadapan Rabb. Dua helai kain putih menjadi simbol kesederhanaan dan kematian yang akan datang. Inilah awal dari penyucian jiwa, tempat ego dihancurkan dan hati disucikan.
Thawaf mengajarkan bahwa kehidupan berputar di sekitar Allah, bukan ego manusia. Ketika jemaah mengelilingi Ka’bah, sejatinya mereka sedang menegaskan bahwa Allah adalah pusat kehidupan mereka. Tak ada tempat lagi bagi kesombongan dan kelalaian. Di tengah lautan manusia yang bertalbiyah, setiap jantung berdetak dengan satu tujuan: ridha-Nya.
Sa’i antara Shafa dan Marwah adalah pelajaran tentang ikhtiar dan tawakal. Hajar, seorang ibu, berlari-lari kecil mencari air untuk anaknya yang kehausan di tengah padang pasir. Dari ketekunannya itulah Allah mengeluarkan air zamzam, sumber kehidupan. Sa’i mengajarkan bahwa keajaiban akan hadir bila kita berusaha dan berserah dalam waktu yang sama.
Baca Juga: Bulan Solidaritas Terhadap Rakyat Palestina
Wukuf di Arafah adalah puncak haji, saat di mana langit begitu dekat dengan bumi. Di sana, dosa-dosa dihapuskan, air mata bertumpah, dan doa-doa dilangitkan. Wukuf adalah simulasi dari padang mahsyar, mengingatkan kita bahwa suatu hari kita semua akan berdiri di hadapan Allah untuk dihisab. Maka, betapa berharganya waktu di Arafah, untuk bermuhasabah dan bertobat dengan sungguh-sungguh.
Melempar jumrah bukan sekadar simbolik melempar batu. Ia adalah deklarasi perang terhadap godaan syaitan. Setiap lontaran mengandung tekad kuat untuk meninggalkan keburukan dan hawa nafsu. Di sinilah seorang Muslim memproklamasikan dirinya sebagai pejuang kebaikan, melawan bisikan jahat yang menggelincirkan manusia dari jalan kebenaran.
Menyembelih hewan kurban adalah ekspresi kepasrahan seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim dan putranya, Ismail. Ini bukan soal daging dan darah, tapi tentang ketaatan total kepada Allah. Ia adalah pelajaran tentang pengorbanan, bagaimana seorang hamba harus siap melepaskan apa pun yang dicintainya demi taat pada perintah-Nya.
Setelah seluruh rangkaian manasik haji usai, seorang haji yang mabrur bukanlah orang yang sekadar telah menyelesaikan ritual, melainkan yang pulang dengan ruh yang baru, hati yang bersih, dan tekad untuk hidup lebih baik. Ia menjadi pribadi yang lebih lembut, dermawan, jujur, dan adil. Sebab, haji sejati adalah transformasi batin, bukan sekadar prestasi ibadah.
Baca Juga: Menetapi Jama’ah, Menjaga Diri dari Zaman Penuh Luka
Haji mengajarkan umat Islam bahwa spiritualitas tidak terpisah dari kemanusiaan. Menunaikan haji seharusnya membuat seseorang lebih peka terhadap penderitaan sesama, lebih terlibat dalam kebaikan sosial, dan lebih bertanggung jawab dalam kehidupannya. Haji bukan akhir, tetapi awal dari perjalanan hidup yang lebih berarti.
Setiap tahun, jutaan jiwa datang dari segala penjuru dunia untuk berhaji. Mereka berbeda warna kulit, bahasa, dan budaya, tetapi disatukan dalam satu kalimat suci: Labbaik Allahumma labbaik. Ini adalah bukti nyata dari ukhuwah Islamiyah dan kekuatan umat Islam bila bersatu dalam iman dan tujuan.
Menapaki jejak Nabi dalam ibadah haji adalah bentuk cinta dan keteladanan. Nabi Ibrahim mengajarkan kepasrahan, Hajar mengajarkan perjuangan, Nabi Ismail mengajarkan keikhlasan, dan Nabi Muhammad SAW menyempurnakannya dengan kasih dan syariat. Maka, setiap jemaah haji seolah sedang menulis ulang sejarah suci tersebut dalam dirinya sendiri.
Haji juga menjadi pengingat akan kefanaan dunia. Seorang haji yang melihat jutaan manusia berdesakan, menyaksikan kematian di tanah suci, dan merasakan kebersamaan sejati, pasti akan pulang dengan perspektif baru. Dunia tak lagi menjadi tujuan utama, tetapi hanya ladang untuk menanam amal demi akhirat yang kekal.
Baca Juga: Dialog dan Experiential Learning Pada Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidr
Dalam haji, kita dilatih untuk sabar menghadapi kesulitan, ikhlas menjalani perintah, dan bersyukur atas setiap nikmat. Semua ujian di tanah suci—panas terik, antrean panjang, hingga kelelahan fisik—adalah sarana pendidikan jiwa agar menjadi lebih kuat dan matang.
Haji sejatinya adalah refleksi dari kehidupan. Dari kelahiran (ihram), perjalanan (manasik), perjuangan (sa’i dan jumrah), kematian (wuquf), hingga kebangkitan (tahallul dan kembali ke rumah). Maka, siapa yang memahami haji dengan hati, ia akan menjalani hidup dengan lebih arif dan bertanggung jawab.
Akhirnya, haji adalah janji jiwa kepada Allah bahwa ia akan tetap istiqamah. Ia bukan tujuan akhir, melainkan titik balik. Maka, semoga setiap langkah kita di bumi, sebagaimana langkah-langkah di tanah suci, senantiasa menapaki jejak para nabi—menuju Allah, dengan hati yang tunduk dan jiwa yang mencinta.[]
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: 14 Poin Krusial KUHAP Baru, Publik Soroti Risiko Pelemahan Hak Asasi












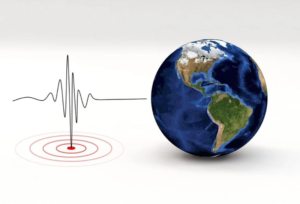
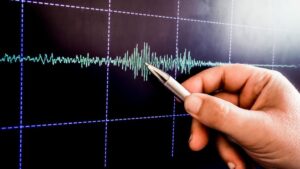





















 Mina Indonesia
Mina Indonesia Mina Arabic
Mina Arabic Mina Preneur
Mina Preneur