Oleh Arief Rahman, Wartawan Kantor Berita MINA
SEJAK lahir di Yunani Kuno, Olimpiade tidak hanya soal rekor dan medali; ia juga memuat jeda moral dari kekerasan melalui ekecheiría, gencatan senjata agar kontingen dan penonton dapat tiba di Olympia dengan aman, sehingga gagasan modern tentang “olahraga untuk perdamaian” dan prinsip Piagam Olimpiade, bahwa “praktik olahraga adalah hak asasi manusia yang dijalankan tanpa diskriminasi apa pun”, bukan sekadar slogan melainkan janji etik yang menyertai setiap perlombaan.
Sejarah memperlihatkan panggung olahraga tak pernah benar-benar steril dari politik. Di polis-polis Yunani, kemenangan atlet sering dibaca sebagai prestise politik kota-negara; dalam era modern, boikot, sanksi, hingga klausul hak asasi manusia menyertai kontrak tuan rumah, sehingga “non-diskriminasi” dan “otonomi organisasi olahraga” menjadi dua pilar yang terus diuji ketika dunia menghadapi perang, pendudukan, dan krisis kemanusiaan.
Soekarno, Asian Games 1962, dan GANEFO: Solidaritas yang Menjadi Sikap
Baca Juga: Ketika Rumah Tangga Retak Karena Ego yang Tak Terjaga
Indonesia punya bab penting ketika Presiden Soekarno menolak partisipasi Israel (dan Taiwan) pada Asian Games 1962 di Jakarta sebagai wujud keberpihakan pada bangsa-bangsa tertindas, dan keputusan itu berujung pada skors IOC sekaligus kelahiran GANEFO (Games of the New Emerging Forces) sebagai ajang tandingan yang menegaskan “olahraga tidak netral terhadap penjajahan”.
Atlet yang tampil di GANEFO kemudian mendapat larangan tampil di Olimpiade Tokyo 1964, sehingga garis besar sikap Indonesia sejak awal terlihat: olahraga dipahami sebagai ruang etis yang menyatu dengan politik luar negeri anti-kolonial dan dukungan terhadap Palestina.
Sengkarut Terbaru: Rekomendasi IOC dan Penolakan Atlet Senam Israel
Kontroversi kembali mengemuka ketika Komite Olimpiade Internasional (IOC) merekomendasikan agar federasi internasional tidak menggelar event di Indonesia setelah pemerintah menolak visa atlet senam Israel untuk Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Jakarta, dan pembahasan peluang Indonesia menjadi tuan rumah event Olimpiade ditangguhkan sampai ada jaminan akses nondiskriminatif. Sebelumnya, Indonesia juga kehilangan status tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 setelah muncul penolakan terhadap kehadiran tim Israel, sehingga terlihat pola bahwa sikap politik-etis Indonesia berbiaya pada ranah penyelenggaraan.
Baca Juga: Ekopedagogi Islam, Belajar dari Alam yang Tergenang
Dalam kacamata hak asasi, IOC menegaskan dua hal yang tampak bertabrakan dalam praktik: hak setiap atlet untuk berpartisipasi “tanpa diskriminasi” serta otonomi olahraga dari intervensi politik negara. Benturan muncul saat etika kemanusiaan sebuah bangsa—yang menolak normalisasi terhadap praktik pendudukan—berhadapan dengan aturan universal penyelenggaraan olahraga global.
Pertanyaan Konsistensi: Rusia–Ukraina vs Israel–Palestina
Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, IOC menerapkan skema athletes under neutral status (AIN) bagi atlet Rusia dan Belarus: tidak boleh membawa bendera, lagu kebangsaan, maupun tampil sebagai tim nasional, bahkan ada penyaringan bagi atlet yang berafiliasi militer atau mendukung perang.
Namun terhadap Israel, yang di mata banyak pihak dikaitkan dengan praktik pendudukan, tidak ada sanksi kolektif setara; yang justru menerima konsekuensi adalah negara tuan rumah yang menolak kehadiran kontingen Israel. Perbandingan kebijakan ini melahirkan persepsi bias: agresi antarnegeri memunculkan pembatasan simbol kenegaraan Rusia, sedangkan kasus pendudukan tidak menghasilkan pembatasan serupa, dan ketika tuan rumah menyatakan keberatan atas dasar kemanusiaan, ia yang “dihukum” dengan risiko hosting.
Baca Juga: Trump dan Kejujuran yang Menelanjangi Dosa-dosa AS
Etos Atlit: Olahraga Tak Terpisah dari Kemanusiaan
Pada 20 Juli 2021, IOC secara resmi menambahkan kata “Together” (Communiter) sehingga motto kini berbunyi: “Citius, Altius, Fortius, Communiter (Faster, Higher, Stronger — Together)”, menegaskan bahwa kemajuan olahraga bermakna bila dicapai bersama.
Sejalan dengan semangat motto IOC yang baru bagi atlet, pelatih, dan penyelenggara, akar makna olahraga ialah martabat manusia, sportivitas, solidaritas, dan keselamatan, karena itu kalimat “olahraga tidak bisa dipisahkan dari semangat kemanusiaan” adalah pedoman praktis, bukan hiasan.
Artinya, suara untuk korban perang dan pendudukan tetap perlu disalurkan secara bermartabat; integritas sistem olahraga harus dijaga agar tidak menjadi panggung impunitas; lembaga global berkewajiban konsisten dalam menegakkan aturan tanpa menutup mata pada realitas pelanggaran; dan nurani atlet berhak hidup berdampingan dengan disiplin kompetisi.
Baca Juga: Bulan Solidaritas Palestina, Terus Bergerak untuk Al-Aqsa dan Palestina
Dukungan untuk pemerintah
Dalam konteks ini, dukungan pada pemerintah menjadi relevan dan perlu ditegaskan: Menpora Erick Thohir menyatakan “kami berpegang pada prinsip untuk menjaga keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik” seraya menautkan respons atas rekomendasi IOC pada mandat UUD 1945, sekaligus menegaskan bahwa olahraga Indonesia harus tetap “menjadi duta dan cerminan kedigdayaan bangsa” di panggung dunia; di PBB (23 September 2025).
Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan “dukungan penuh Indonesia untuk solusi dua negara—Palestina merdeka, dengan keselamatan dan keamanan Israel yang dijamin”, seraya mengajak dunia “mengakhiri tragedi Gaza” melalui langkah damai yang kredibel; dua pesan ini selaras dengan garis besar artikel ini: olahraga dan kemanusiaan bukan dua dunia terpisah, dan kebijakan olahraga yang berkeadilan hanya akan kuat bila berpijak pada konstitusi, nurani, dan konsistensi penerapan standar global. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Ketika Cinta Tak Lagi Bernilai: Perceraian Jadi Jalan Cepat
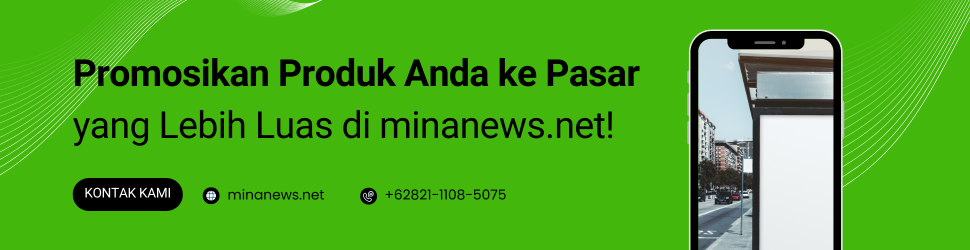





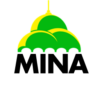



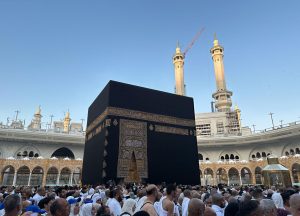










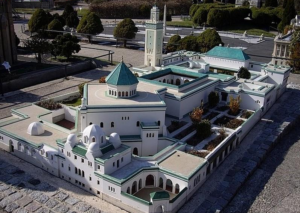








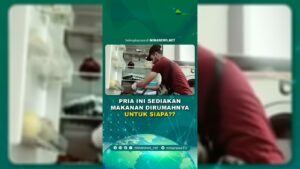



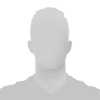
 Mina Indonesia
Mina Indonesia Mina Arabic
Mina Arabic Mina Preneur
Mina Preneur