Oleh T. Taufiqulhadi, Pemerhati Masalah Timur Tengah
Setelah setahun Perang Gaza, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan kabinet ultra kanannya, di depan rakyatnya dan di mata masyarakat internasional, telah gagal dalam dua “perang total” di Gaza: gagal menang total dalam perang Israel-Hamas dan gagal penghancuran total Hamas.
Masyarakat internasional, yang awal pada tanggal 7 Oktober sempat memberi dukungan kuat kepada Netanyahu dan rakyat Israel terhadap apa yang mereka katakan sebagai serangan brutal dan kejam Palestina ke wilayah Israel, kini menjadi waswas kepada Netanyahu apakah mereka bukan sedang memelihara anak macan di halaman belakang mereka.
Netanyahu sama sekali tidak mengindahkan pandangan masyarakat internasional dan bahkan rakyatnya sendiri bahwa Hamas tidak bisa dihancurkan karena Hamas itu bukan saja sebuah organisasi (perang) tapi juga sebuah ideologi. Ideologi tidak bisa dihancurkan sejauh masih relevan, hanya berganti pendukungnya saja. Mereka mengusulkan untuk berunding, berfokus untuk pengembalian para sandera di tangan Hamas.
Baca Juga: Ayah yang Tak Sempurna Tapi Selalu Berusaha
Tapi apakah memang Netanyahu tidak tahu soal Hamas sebuah ideologi itu? Saya tidak yakin bahwa ia tidak tahu. Tetapi justru ia sedang mengenderai Perang Gaza untuk tujuan-tujuan lain yang telah direncanakan yaitu merampas sebanyak mungkin tanah Palestina. Rencana perampasan sebanyak mungkin Tanah Palestina tidak hanya Gaza tapi juga di Tepi Barat, bukanlah sebuah politik retoris Netanyahu. Tapi itu nafsu lama, yang tidak pernah disingkirkan oleh semua pemimpin Israel terutama figur-figur politik dan partai politik sayap kanan dan ultra kanan.
Dalam kabinet pemerintahan Netanyahu sekarang ini berkumpul hampir semua pemimpin politik dan partai politik sayap kanan dan ultra kanan seperti Zionis Keagamanan yang diwakili oleh Menteri Keuangan Benazel Smotrich dan Otzma Yehudit yang diwakili Menteri Warisan Amaihai Eliyahu yang ingin mengusir orang Arab dari Palestina. Sementara, Likud, partai Netanyahu sendiri, menyumbangkan sejumlah kader ultra kanannya juga dalam kabinet ini.
Platform kaum Utra kanan itu ada tiga yaitu: perluasan permukiman Yahudi; menentang pembentukan negara Palestina; dan penerapanan kedaulatan Israel terhadap Jalur Gaza, Tepi Barat dan Jerusalem Timur. Smothrich dan Eliyahu ini dua menteri yanag selalu berada di samping Netanyahu sekarang setelah kabinet Perang Israel dibubarkan, paling banyak mempengaruhi kebijakan Netanyahu.
Dengan banyaknya politisi dan partai ultra kanan dalam kabinet Netanyahu, Perang Gaza menjadi menjadi momentum bagi kabinet ini untuk melaksanakan gagasan-gagasan mereka di Palestina. Mereka akan merelisir gagasan merampas semua tanah Palestina dan mengusir sebanyak mungkin warga Palestina dengan cara menciptakan apa yang disebut Menteri Pertaninan Avi Dichter (Likud) sebagai “Nakba Gaza”, dari bahasa Arab yang artinya “malapetaka besar”, yang merujuk kepada pengusiran 700.000 warga Palestina yang diikuti dengan pembentukan negara Israel pada 1948.
Baca Juga: Menetapi Jama’ah, Menjaga Diri dari Zaman Penuh Luka
Dalam gagasan ini, perang Gaza harus diperluas ke Tepi Barat. Selama Perang Israel-Hamas ini, Pasukan Israel telah melakukan sejumlah serangan darat ke Tepi Barat terutama ke Jenin dan Tulkarem. Tentara Isarel bahu-membahu dengan pemukim Israel menyerang wilayah pendudukan itu, yang menyebabkan setidaknya 693 orang telah tewas, sekitar 100 orang adalah anak-anak.
Jadi kalau digabung dengan korban tewas di Gaza per hari ini sebanyak 41.788 jiwa dan di Tepi Barat 693 jiwa, maka total orang Palestina yang terenggut nyawa karena kebiadaban Israel menjadi 42.481 jiwa. BBC melaporkan, Gaza memang masih terlihat sampai sekarang tetapi Gaza yang penuh dengan kematian dan kuburan.
Jika gagasan kaum ultra kanan itu terlaksana, yaitu merampas semua tanah Palestina dan mengusir sebanyak mungkin warga Palestina, maka korban jiwa di Tepi Barat masih belum berhenti pada anggka 693 orang. Mungkin bisa saja mendekati korban jiwa yang terjadi di Jalur Gaza.
Ke mana negara-negara Arab dan Amerika?
Baca Juga: Dialog dan Experiential Learning Pada Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidr
Sikap negara-negara Arab sangat menarik jika dilihat selama Perang Israel-Hamas ini. Para pemimpin negara-negara Arab hanya menyampaikan retorika dan diplomasi lunak saja yang menunjukkan posisi negara-negara sangat lemah vis a vis Israel (dan Amerika Serikat). Negara-negara Arab tidak berdaya karena ketergantungan ekonomi dan militer kepada Amerika Serikat dan Barat. Mereka menganggap, berhadapan dengan Israel sama dengan mengorban kestabilan politik dan ekonomi karena khawatir pembalasan AS.
Negara dan para pemimpin Arab sekarang sangat berbeda dengan negara dan pemimpin Arab tahun 1960-an dan 1970-an. Pada era tersebut, ekor kekalahan Arab dalam Perang Enam Hari pada tahun 1967, dan kekalahan dalam Arab dalam Perang Youm Kipur pada tahun 1973, bersatu-padu untuk membuat perhitungan kepada Israel dan negara-negara Barat pendukung Israel.
Terkenal sekali pada saat itu, negara-negara Arab penghasil minyak utama seperti Arab Saudi, Kuwait, UEA, Qatar, Suariah, Irak dan Libya, secara bersama-sama, melancarkan pembalasan dengan melakukan embargo minyak ke semua negara-negara Barat pendukung Israel, yang menyebabkan ekonomi Amerika dan Eropa Barat lumpuh.
Bukan respon politik saja yang mereka ambil, tapi dunia akademis pun bereaksi dengan mempertanyakan: kenapa Arab kalah dan Barat menang. Karena pertanyaan itu, saat itu muncul seumlah ilmuan Arab kelas berat yang masih dihormati sekarang seperti diantaranya Abid al-Jabir, Hasan Hanafi dan Nasr Hamid Zayd yang mengritik habis warisan pemikiran Arab yang stagnan itu.
Baca Juga: 14 Poin Krusial KUHAP Baru, Publik Soroti Risiko Pelemahan Hak Asasi
Orang Arab dan Islam, menurut mereka, tidak maju dan kalah karena telah berhenti di tempat dalam pemikiran. Mereka hanya mengulang-ulang saja warisan Arab-Islam lama seperti hukum Islam yang dikodifikasi pada abad ke-10 itu. Para ilmuan raksasa itu, yang hingga sekarang dapat kita ikuti pemikiran mereka, menyerukan agar masyarakat Arab menjadi lebih dewasa menyikapi modernitas.
Jadi Ekor kekalahan Perang Enam Hari dan Youm Kipur itu, bukan hanya membuat bangsa Arab terhenyak dari jagad politiknya tetapi membuat dunia akademis bergairah dan lebih kuat menggugat cara berpikir dan tradisi yang tidak mendorong kemajuan.
Tapi perang di Gaza yang dianggap sebagai situs pembantaian manusia terbesar di abad ini, tidak menggugah apapun di kalangan orang Arab: tidak tergugah secara politik dan tidak berdampak secara akademis. Pembunuhan lebih 40.000 orang terhadap saudara mereka itu dianggap sebagai tragedi biasa yang terjadi di tempat jauh, terhadap orang-orang yang tidak dikenal.
Para pemimpin Arab menyampaikan sejumlah retorika-retorika kosong dengan tujuan tidak lebih untuk sekedar dapat meredam suara-suara marah warga negaranya. Tapi telah dihitung tidak mengganggu status quo, yaitu tidak merusak hubungan yang telah terbina dengan Amerika Serikat dan Israel.
Baca Juga: Indonesia dan Masa Depan Hutan Tropis Dunia, Langkah Baru Memimpin Konservasi
Saat ini, ada dua negara di mata masyarakat awam Arab paling antagonistis di Timur Tengah yaitu Yordania dan Mesir. Ketika permulaan Perang Hamas-Israel, Mesir menjadi negara yang aktif bertindak sebagai penengah untuk tercapai gencatan senjata, selain itu Mesir memperingatkan agar tidak terjadi pengusiran warga Gaza karena keberadaan penduduk merupakan syarat terbentuk negara Palestina.
Tapi setelah ditunggu-tunggu sekian lama tidak pernah sekali pun Mesir menawarkan status pengungsi kepada warga Palestina yang terusir dan tidak memiliki tempat tinggal lagi dari Gaza. Justru, bekerja sama dengan Israel, menutup Rafah agar korban yang masih hidup itu agar tidak menyusahkan negeri Firaun itu.
Yordania juga serupa, ia memperingatkankan Israel tidak melakukan pengusiran terhadap warga Gaza. Lebih jauh, Yordania juga menggelarkan rumah sakit terbuka dan mengirim tenaga medis serta obat-obatan ke Gaza. Tapi ketika Iran menyerang Israel dalam rangka membela rakyat Palestina, militer Yordania justru mencegat sejumlah rudal dan drone Iran yang melintasi kerajaan tersebut.
Amman berdalih, mereka terpaksa mencegat rudal Iran untuk mengamankan tanah Yordania dari kemungkinan terkena rudal Iran yang menyesar. Tapi rakyat Yordania mengatakan, pemerintahnya mendukung Israel.
Baca Juga: Ancaman Sunyi di Balik Evakuasi Warga Gaza Berkedok Kemanusiaan
Ekor Perjanjian Abraham yang didorong oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 2020, sejumlah negara Teluk telah ikut-serta menjalin hubungan diplomatik dengan Israel seperti UEA dan Bahrain.
Kedua negara tersebut kini bersikap sangat reaktif dan sensitif. Sedikit saja ada gelagat terdapat suara yang mengecam Israel di dalam negeri sehubungan Perang Gaza, aparat keamanan kedua negara itu segera bertindak dengan menciduk pengritik tersebut. Bahrain sangat khawatir, kritik terhadap Perang Gaza akan berubah menjadi gerakan pro-Iran (Syiah). Itu berhubungan lebih 60 persen warga Bahrain adalah pemeluk Syiah. Sementara UEA sangat tergantung kepada jaminan kestabilan politik negara itu kepada Amerika Serikat.
Karena Perjanjian Abraham itu, Arab Saudi pun nyaris membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Netanyahu telah mengumumkan di PBB, tidak lama lagi, negaranya akan menjalin hubungan diplomatik dengan Arab Saudi. Hubungan diplomatik antara kedua negara, kata Netanyahu “akan mampu mencegah skenario jahat Iran”. Tapi rencana itu gagal karena Perang Israel-Hamas.
Pangeran Muhammad bin Salman menggemakan kembali “tekad”-nya dalam rangka meredam kemarahan rakyat Arab Saudi bahwa pembukaan hubungan diplomatik antara kedua negara itu mensyaratkat terbentuknya negara Palestina. Sesungguhnya, ketika Perjanjian Abraham sedang mekar, syarat itu tidak pernah itu mengemuka. Hanya karena terbentur perang Gaza saja, MBS menyembunyikan syarat two states solution.
Baca Juga: Ketika Pelukan Anak Jadi Obat Lelah
Di Washington, Presiden Joe Biden ini mirip orang tua kehilangan ingatan dan mengalami rabun dekat. Biden seperti hidup dalam fantasinya sendiri seakan ia sangat besar pengaruhnya dan sangat dihormati. Padahal, baik sekutu, lembaga-lembaga politik di negaranya dan apa lagi musuh-musuhmya, semua tidak mengindahkan sang presiden gaek ini. Bukan rahasia lagi jika pemimpina dunia yang paling tidak mengindahkan Presiden Amerika Serikat ini adalah Netanyahu, pemimpin dari negara yang dianggapnya sebagai sekutu paling dekat Washington.
Dua pekan lalu, ketika Netanyahu berada di Washington, Biden mencoba memperingatkan Netanyahu untuk tidak mengambil langkah yang berakibat kepada tereskalasi konflik Gaza. Tapi beberapa jam saja, persis di kamar hotel di depan hidung Biden, Netanyahu memerintahkan untuk meledakkan pager yang mengakibatkan puluhan warga Lebanon tewas dan lebih 600 luka-luka. Tidak berhenti sampai di situ, selang beberapa hari saja, Netanyahu memerintahkan kembali untuk menyerang Beirut secara besar-besaran yang mengakibatkan tewasnya Hasan Nasrallah, pemimpin Hezbollah.
Biden juga mengingatkan Iran untuk tidak menyerang kepentingan Amerika dan sekutu dekatnya Israel. “Jangan pernah menyerang kepentingan Israel….jangan… jangan….jangan… !”, katanya mengulang-ulang untuk menegaskan bahwa itu sangat penting. Biden memang mampu melakukan koordinasi dengan sejumlah negara untuk memperkuat upaya perdamaian di Timur Tengah. Tapi dua hari setelah kata “jangan…jangan..jangan,” Biden itu, Iran melancarkan serangan rudal kedua kalinya ke Israel. Biden itu tidak diindahkan sekutunya dan tidak dihormati musuh-musuhnya.
Jadi rakyat Palestina di ulang tahun Perang Gaza yang pertama ini, harus bersiap-siap menghadapi bencana lebih besar di depan hidung saudara-saudaranya yang kini kian sulit bersatu seperti dulu. Arab sekarang bukan Arab seperti dulu.
Baca Juga: Kritik Radikal Ilan Pappe terhadap Proyek Kolonial Israel
*Penulis adalah penulis buku “Satu Kota Tiga Tuhan, Deskripsi Jurnalistik di Yerusalem”
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Pentingnya Narasi dan Literasi dalam Perjuangan Palestina






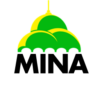



























 Mina Indonesia
Mina Indonesia Mina Arabic
Mina Arabic Mina Preneur
Mina Preneur