Oleh Najla Amalia, Mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
PERNAH merasa gelisah saat melihat teman liburan ke tempat hits, pakai outfit terbaru, atau nongkrong di kafe yang sedang viral? Kalau iya, tenang, kamu tidak sendiri. Fenomena itu dikenal dengan istilah FOMO atau Fear of Missing Out, yaitu rasa takut tertinggal dari orang lain. Dan menurut berbagai penelitian, FOMO kini menjadi salah satu ciri paling khas dari generasi Z.
Generasi Z, mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, dikenal sebagai generasi yang paling akrab dengan teknologi digital. Sejak kecil, mereka sudah bersentuhan dengan gawai, media sosial, dan internet. Teknologi memberi banyak kemudahan: informasi datang secepat kilat, komunikasi bisa dilakukan tanpa batas ruang dan waktu. Namun, di balik kemudahan itu, muncul fenomena baru yang kini menggerogoti keseharian mereka: FOMO (Fear of Missing Out), rasa takut tertinggal dari orang lain.
Banyak orang tua sebenarnya menyadari dilema ini. Di satu sisi, anak harus melek teknologi agar tak tertinggal zaman. Tapi di sisi lain, terlalu dalam tenggelam di dunia digital bisa menjerumuskan ke perilaku konsumtif, cemas sosial, bahkan krisis moral. Media sosial, yang awalnya alat komunikasi dan ekspresi, kini sering berubah menjadi panggung pamer kehidupan.
Baca Juga: Belajarlah Bahagia dengan Hal-Hal Sederhana
Aplikasi seperti TikTok dan Instagram menjadi ruang untuk menunjukkan “siapa diri kita”, atau lebih tepatnya, “siapa yang ingin kita tampilkan”. Tak sedikit remaja menggunakan media sosial bukan untuk berbagi pengetahuan, tapi untuk mengikuti tren: dari outfit kekinian, gaya make up, hingga nongkrong di kafe hanya demi membuat konten yang “tidak ketinggalan zaman”.
Survei Populix menunjukkan, Gen Z memiliki kecenderungan belanja impulsif akibat FOMO. Mereka sering membeli barang hanya karena tren di media sosial, bukan karena kebutuhan. Ironisnya, banyak barang itu akhirnya tak digunakan. Fenomena ini juga merembet ke cara berpakaian dan pergaulan. Sebagian remaja berlomba tampil fashionable dengan pakaian ketat atau terbuka, bukan karena kebutuhan estetika, tapi demi pengakuan sosial.
Padahal, dalam QS. Al-Ahzab ayat 59, Allah telah menuntun umat Islam agar berpakaian dengan penuh kehormatan dan kesopanan. Nabi Muhammad ﷺ pun berjuang keras mengangkat martabat perempuan agar dihormati, bukan dijadikan objek tontonan. Namun kini, sebagian generasi muda justru menjadikan tubuh sebagai alat untuk eksistensi digital.
Fenomena serupa juga terjadi di kalangan remaja laki-laki. Ajakan teman untuk balapan liar, merokok, atau ikut tren ekstrem sering membuat mereka merasa wajib ikut agar tidak disebut “kudet” (kurang update) atau “nggak keren”. Tekanan sosial semacam ini menjadi bentuk FOMO yang lebih halus tapi berbahaya.
Baca Juga: Anak yang Didengar, Tumbuh Lebih Bahagia
Ungkapan populer di media sosial kini terasa sangat relevan:
“Kita begitu rajin mengelap layar ponsel agar tak berdebu, namun lupa menyentuh mushaf yang lama tertutup debu. Padahal di sanalah cahaya yang menerangi hati, bukan hanya layar yang menerangi wajah di malam hari.”
Penelitian Kaloeti dkk (2021) menunjukkan bahwa sekitar 64,6% remaja Indonesia mengalami FOMO akibat penggunaan media sosial. Efeknya nyata: kecemasan, stres, ketidakpuasan sosial, hingga rasa kesepian yang meningkat meski “terhubung” secara digital.
Namun, FOMO bukanlah kutukan yang tak bisa dihindari. Generasi Z tetap bisa menjadi generasi yang bijak digital. Kuncinya adalah kesadaran diri, menyadari batas antara kebutuhan dan keinginan, antara eksistensi dan pencitraan. Tidak perlu gengsi hidup sederhana, karena nilai seseorang tidak diukur dari jumlah likes atau followers, tetapi dari seberapa tenang hati dan bermanfaatnya ia bagi orang lain.
Baca Juga: JENESYS 2025 Ditutup, Jepang Dorong Pemuda Islam Indonesia Jadi Penghubung Dua Peradaban
Para orang tua pun perlu menjadi teladan, bukan hanya pengawas. Mereka bekerja keras memenuhi kebutuhan keluarga, maka sudah semestinya anak-anak tidak hidup berlebihan hanya demi citra media sosial.
Solusinya sederhana tapi bermakna: kurangi interaksi dengan lingkungan yang suka flexing, dan kembalikan tujuan awal bermedia sosial, untuk belajar, berbagi, dan memberi inspirasi. Karena sejatinya, yang paling berharga bukanlah “update” di dunia maya, melainkan upgrade diri di dunia nyata. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Kemenag Reviu Kurikulum Lembaga Pendidikan Al-Quran dan Madrasah Diniyah






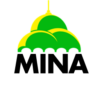
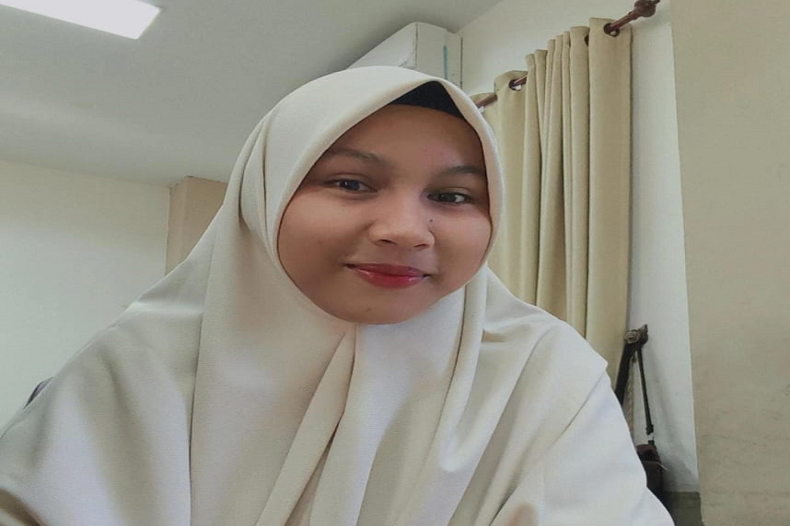



























 Mina Indonesia
Mina Indonesia Mina Arabic
Mina Arabic Mina Preneur
Mina Preneur