THOHRIYAH binti Yoesoef Mahfudz satu dari sekian muslimah yang jejak kehidupannya berjalan dari satu lokasi hijrah ke tempat hijrah lainnya. Ia yang Desember 2024 ini genap berusia 76 tahun beberapa kali ikut hijrah mendampingi suaminya, Abdul Hanan menembus belantara Sumatera tahun 1976.
Memboyong semua anggota keluarga untuk amanah dakwah, kisah pindah dari satu tempat ke tempat lain, tentu tidak mudah Thohriyah jalani, apalagi Ia harus mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Jakarta, yang saat itu kepastian penghasilan materi lumayan lebih baik dan pasti.
Thohriyah mengabdi sebagai seorang guru PNS di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, sejak tahun 1970. Kemudian pada tahun 1976, Thohriyah, mengikuti suami mendapatkan amanah berdakwah ke Pagar Alam, Sumatera Selatan. Saat itu, Ia telah memiliki empat anak, anak pertamanya Susi saat itu berusia 4 tahun, sementara yang paling kecil, Wahyu, saat itu baru berumur 2 bulan.
Setelah proses pengunduran diri sebagai PNS diterima di tempatnya mengabdi, dengan tekad bulat Ia berhijrah meninggalkan Jakarta. Perjalanan dari Tanjung Priuk ke Pagar Alam saat itu tentu tidak mudah, mengingat kondisi anak-anak yang masih kecil dan perjalanan yang cukup panjang. Namun, Ia memantapkan hati untuk memulai hidup baru di Pagar Alam dengan kondisi yang jauh berbeda dengan Jakarta, bahkan dengan tanah kelahirannya di tatar Pasundan, Sukabumi.
Baca Juga: Terpilih Lagi jadi Ketua MUI, Ini Profil Lengkap KH Anwar Iskandar
Anak-anak Thohriyah harus terbiasa dengan keadaan yang serba terbatas. Salah satu tantangan terbesar adalah memberi makan anak yang masih kecil. Makanan yang ada sangat terbatas, dan sering kali harus dibagi, meski tidak cukup untuk satu keluarga saat itu. Thohriyah harus benar-benar dapat memastikan anak-anaknya tetap makan meskipun dengan makanan yang sangat sederhana.
Makanan yang tersedia sangat terbatas, hanya daun singkong, kerupuk singkong, dan sedikit nasi untuk makanan sehari-hari. Pada tahun 1979, pendapatan keluarga hanya sekitar 250 rupiah per bulan, yang tentu saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Kondisi itu semakin sulit karena penghasilan sangat terbatas. Uang yang diterima digunakan untuk kebutuhan yang sangat dasar, seperti sabun dan untuk lampu penerang,” katanya.
Setelah menetap di Pagar Alam selama kurang lebih tiga tahun setengah, Ia menghadapi masa-masa sulit. Ketika itu Ia mengandung lagi, kemudian memutuskan kembali ke Tanjung Priuk untuk melahirkan. Setelah proses persalinan selesai, umur anaknya baru 2 bulan, Ia dan keluarganya mendapat amanah, tapi tidak kembali ke Pagar Alam, melainkan ke Dusun Muhajirun, Negararatu, Lampung Selatan, di mana saat itu juga sedang proses perintisan pesantren Al-Fatah.
Baca Juga: Sheikh Hasina, Dari Dominasi Politik ke Vonis Hukuman Mati
Hijrah ke Muhajirun terjadi pada tahun 1979. Di sana seperti sebelumnya di Pagar Alam, Thohriyah juga mengajar anak-anak di Muhajirun. Satu tahun di sana, Ia dan seluruh anggota keluarganya pindah lagi ke Panaragan, Lampung Utara. Panaragan saat itu masih berupa hutan belantara. Mereka dan beberapa orang lainnya yang mendapat amanah, memulai semuanya dari nol, membabat hutan, membuka lahan, dan membangun rumah untuk memulai kehidupan baru.
Di Panaragan, hanya sempat membangun tiga rumah dan satu masjid kecil. Rumah-rumah tersebut berdiri di atas tanah yang masih berupa hutan belantara. Saat itu, lingkungan di sekitarnya masih sangat sepi, dengan hanya beberapa pohon buah-buahan dan tanah kosong.
“Anak-anak bermain di tengah alam Sumatera yang masih liar, sementara suasana kampung masih sunyi,” katanya.
Hijrah ke Cileungsi
Baca Juga: Zohran Mamdani, Jejak Anak Imigran Muslim Merebut Panggung Amerika
Oktober 1980, Thohriyah dan suaminya pertama kali ke Cileungsi. Bogor. Bersama anak-anak, mereka mengawali hidup di kawasan yang masih berupa hutan dan pepohonan bambu yang lebat. Saat itu hanya ada jalan setapak untuk masuk ke Dusun Pasirangin, dengan berjalan kaki dari jalur utama, kini kawasan itu Jalan Narogong Raya. Pohon bambu yang lebat di kiri kanan jalan saat dilalui, seperti menutup kawasan Pasirangin dari dunia luar.
Thohriyah masih ingat, di kawasan itu seperti tidak tampak kehidupan, namun saat masuk lebih dalam ternyata ada kampung yang dihuni beberapa orang. Di situ, Ia dan rombongan lain yang sudah lebih dulu datang terlibat dalam proses pembangunan awal Pondok Pesantren Al-Fatah,Cileungsi. Rumah-rumah kecil, mushala sederhana mulai didirikan.
“Saat tiba pertama kali, saat itu bangunan yang ada masih sangat sederhana. Sebagian besar hanya berupa rangka tanpa dinding, dan beberapa lainnya hanya memiliki atap genteng,” katanya mengingat awal ia menetap di Cileungsi.
Saat itu, Tohriyah dan keluarga bersama rombongan tiba dengan beberapa orang lainnya, seperti Ustadz Aji Muslim dan istri, Pak Ridwansyah dan keluarga, serta beberapa tukang bangunan. Bangunan pertama yang difungsikan adalah sebuah rumah kecil yang digunakan untuk tempat tinggal bersama.
Baca Juga: Mengenal Sosok Hemedti Komandan RSF dan Sudan yang Terbelah
Muslimat tinggal di rumah tersebut, sementara suami mereka dan para tukang, tidur di bangunan kini menjadi salah satu ruang belajar santri. Untuk memasak, mereka mendirikan dapur umum. Semua masak dan makan bersama selama kurang lebih satu tahun pertama. Kehidupan sangat sederhana, bahan makanan utama berupa beras dan ikan asin yang dikirim dari para dermawan.
Untuk kebutuhan air minum, mereka harus mengambil dari sumur dengan menggunakan timba. Tidak ada listrik, apalagi telepon. Penerangan hanya menggunakan lampu minyak. Mesin Diesel mulai digunakan pada akhir tahun 1980-an, sementara listrik baru tersedia sekitar tahun 1990-an.
Pada tahun 1982, barulah dibuka kelas tarbiyah pertama Al-Fatah Cileungsi. Bangunannya sangat sederhana, hanya satu ruang kelas dengan dinding dari geribik dan lantai yang dilapisi semen kasar. Murid-murid berdatangan dari Tanjung Priuk Jakarta Utara dan dari Pagar Alam, Lampung. Meskipun fasilitas sangat terbatas, semangat untuk belajar dan mengajar tetap tinggi. Saat itu, kata Thohriyah para santri belajar di bawah pohon rambutan, santri menulis di atas tikar yang digelar seadanya.
Kehidupan sangat sederhana. Barang-barang yang dibawa dari tempat asal hanya pakaian ala kadarnya dan beberapa buku. Untuk menyimpan baju dibuat dari kardus bekas, tempat tidur terbuat dari bambu yang dijejerkan, tanpa bantal atau kasur. Meskipun begitu, kata Thohriyah, semua keluarga hidup rukun dan saling membantu. Saat itu, santri sering dititipkan di rumah-rumah warga.
Baca Juga: Hassan al-Turabi Pemikir Kontroversial dari Sudan
“Muslimin dan muslimat dipisahkan, dan setiap keluarga menampung beberapa anak. Hubungan yang terjalin antara santri dan keluarga yang menampungnya menjadi sangat erat, bahkan hingga sekarang, mereka sudah dianggap seperti keluarga sendiri,” katanya.
Perjalanan Thohriyah dari satu tempat ke tempat lainnya, meninggalkan jejak kenangan yang asyik dikisahkan namun tentu haru, pedih, dan sedih saat dijalani ketika itu. Bisa jadi ada tangis tak bersuara dan bulir air mata kesedihan yang tak ditampakkan, termasuk untuk anak-anaknya saat itu. [annisa novi alifa, dini istiqomah]
Baca Juga: Sunan Drajat: Dakwah Kasih Sayang yang Menyentuh Hati






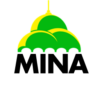




























 Mina Indonesia
Mina Indonesia Mina Arabic
Mina Arabic Mina Preneur
Mina Preneur