KUNJUNGAN Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Arab Saudi pada Selasa, 13 Mei 2025 menandai langkah strategis dalam kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah. Dengan fokus pada perluasan Abraham Accords, pencabutan sanksi terhadap Suriah, dan penguatan hubungan ekonomi dengan Arab Saudi, kunjungan ini mencerminkan upaya AS untuk membentuk ulang tatanan geopolitik kawasan.
Berbicara di sebuah Forum Investasi di Riyadh, Trump menyatakan harapannya agar Arab Saudi segera bergabung dengan Abraham Accords, serangkaian perjanjian normalisasi antara Israel dan negara-negara Arab yang ditetapkan Trump saat masa jabatan pertamanya tahun 2020.
Setelah mendesak Arab Saudi, Trump bertemu dengan Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa di Riyadh pada Rabu, 14 Mei 2025 menandai langkah diplomatik signifikan di Timur Tengah.
Dalam pertemuan tersebut, Trump mengumumkan pencabutan sanksi AS terhadap Suriah dengan bujukan agar Al-Sharaa bergabung dengan Abraham Accords, yang bertujuan menormalisasi hubungan dengan Israel.
Baca Juga: Pengusiran Massal di Tepi Barat Meningkat Tajam
Al-Sharaa secara diplomatis menyatakan komitmennya terhadap stabilitas regional dan menandai perubahan arah kebijakan Suriah.
Meskipun Al-Sharaa tidak sepenuhnya menutup kemungkinan normalisasi di masa depan, ia menyatakan bahwa Suriah saat ini terlalu lemah untuk terlibat dalam konflik baru atau perjanjian geopolitik besar.
Ia juga mengkritik tindakan militer Israel di wilayah Suriah dan menekankan bahwa prioritasnya adalah menghentikan pelanggaran terhadap kedaulatan Suriah dan menghindari eskalasi lebih lanjut.
Al-Sharaa juga telah mengumumkan rencana untuk membentuk pemerintahan transisi yang inklusif, menyusun konstitusi baru, dan mengadakan pemilihan umum dalam 3-5 tahun ke depan. Ia juga berkomitmen untuk menarik investasi asing, memberantas korupsi, dan menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung.
Baca Juga: Duka Sumatra dan Jalan Kebangkitan Umat
Al-Sharaa menekankan bahwa rekonstruksi Suriah harus didasarkan pada prinsip-prinsip modern yang menjamin keadilan dan hak bagi semua warga negara.
Jadi, meskipun ada tekanan internasional untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, Al-Sharaa memprioritaskan pemulihan internal Suriah. Ia menekankan bahwa rekonstruksi, stabilitas, dan pembangunan institusi yang kuat adalah langkah-langkah krusial sebelum mempertimbangkan kebijakan luar negeri yang signifikan seperti normalisasi hubungan diplomatik.
Sementara itu, Arab Saudi lebih memilih untuk melakukan investasi besar-besaran di Amerika Serikat. Kerajaan tersebut berencana menginvestasikan sekitar USD 600 miliar (sekitar Rp9.800 triliun) di AS selama empat tahun ke depan, sebagai bagian dari strategi ekonomi yang sejalan dengan Visi 2030 untuk mendiversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada minyak.
Bahrain dan Uni Emirat Arab
Baca Juga: Refleksi 48 Tahun Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina
Pada pelaksanaan Abraham Accords, tahun 2020, dua negara di kawasan Timur Tengah, Bahrain dan Uni Emirat Arab (UEA) telah menjalin normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel atas sponsor AS.
Normalisasi yang dilakukan Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), dengan Israel beralasan langkah strategis dan geopolitik yang saling terkait.
Tentu, desakan AS di bawah pemerintahan Donald Trump, memainkan peran sentral dalam mendorong normalisasi tersebut. AS menawarkan insentif politik, ekonomi, dan militer sebagai bagian dari kesepakatan.
UEA diberi akses untuk membeli jet tempur siluman F-35, yang sebelumnya tidak diperbolehkan karena komitmen AS menjaga keunggulan militer Israel. AS juga menjanjikan peningkatan kerja sama ekonomi dan teknologi, serta jaminan keamanan terhadap ancaman dari Iran.
Baca Juga: Bulan Solidaritas Terhadap Rakyat Palestina
Demikian juga, Bahrain dan UEA, seperti Israel, dibuat pada satu garis, memandang Iran sebagai ancaman utama di kawasan.
Iran dituding mendukung kelompok-kelompok milisi bersenjata yang dianggap mengancam kestabilan dalam negeri mereka, seperti Hezbollah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan kelompok-kelompok di Bahrain.
Sehingga normalisasi dengan Israel dipandang sebagai bagian dari koalisi regional anti-Iran, yang pasti didukung oleh AS. AS sendiri yang membuat agenda setting normalisasi itu.
Israel juga telah disetting memiliki teknologi keamanan, pertahanan siber, dan inovasi tinggi yang menarik bagi negara-negara Teluk. Maka, dengan normalisasi, Negara-negara itu akan bisa mengakses teknologi keamanan canggih dari Israel, serta bisa memperkuat kemampuan militernya melalui kerja sama intelijen.
Baca Juga: Menetapi Jama’ah, Menjaga Diri dari Zaman Penuh Luka
Walaunpun tentu saja kecanggihan militer dan intelejen Israel itu ternyata porak-poranda dihantam aksi Badai Al-Aqsa (Thufanul Aqsa) para pejuang dari Jalur Gaza, dengan senjata yang dipandang lebih remeh dan pasukan yang lebih sedikit.
Bahrain dan UEA juga mengklaim bahwa salah satu alasan normalisasi adalah untuk menghentikan rencana Israel menganeksasi sebagian Tepi Barat. Namun pada kenyataannya pasukan Zionis Israel tetap memperluas permukiman ilegal di wilayah Palestina. Bahkan terjadi agresi militer Zionis Israel ke Jalur Gaza dalam konflik-konflik besar di 2021 dan 2023–2024.
Peluang Investasi dan Ekonomi
Kedua negara juga melihat peluang pengembangan ekonomi dan investasi dua arah dan akses pasar baru, termasuk potensi kerja sama dalam sektor kesehatan, energi, dan keamanan siber.
Baca Juga: Dialog dan Experiential Learning Pada Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidr
Padahal ekonomi AS sendiri sebenarnya tidak sedang baik-baik saja, menghadapi perubahan lanskap geopolitik global.
Utang nasional AS saat ini sudah melebihi $34 triliun (lebih dari Rp561.895 triliun), angka tertinggi dalam sejarah AS.
Utang tersebut meningkat karena defisit anggaran tahunan yang besar, didorong oleh belanja pertahanan, program sosial, dan stimulus ekonomi selama pandemic tahun-tahun sebelumnya. Meski begitu, AS masih mampu membayar bunga utangnya karena status dolar sebagai mata uang cadangan dunia.
Namun posisi dolar AS mendapat saningan utama, yaitu kekuatan mata uang euro sebagai alternatif yang semakin terasa di kawasan Eropa. Walaupun tantangan utamanya bukan semata terhadap dolarnya, melainkan lebih pada kepercayaan global terhadap kebijakan fiskal dan moneter AS.
Baca Juga: 14 Poin Krusial KUHAP Baru, Publik Soroti Risiko Pelemahan Hak Asasi
Belum lagi ekspansi ekonomi Tiongkok yang menjadi pesaing utama AS dalam ekonomi global, teknologi, dan perdagangan. Tiongkok terus memperluas pengaruh ekonominya melalui inisiatif Belt and Road (One Belt One Road), peningkatan ekspor teknologi tinggi dan dominasi rantai pasokan global.
Posisi AS didesak lagi oleh kemunculan kelompok negara-negara yang tergabung dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan South Afrika), didirikan pada 2009 (awalnya sebagai BRIC pada 2006).
BRICS hendak menantang dominasi Barat dalam sistem keuangan global, termasuk peran dolar.
Maka, negara-negara yang tergabung dalam BRICS mulai membangun New Development Bank sebagai alternatif IMF/World Bank, mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan antaranggota, dan terus berusaha menarik anggota baru, terutam dari negara-negara Muslim.
Baca Juga: Indonesia dan Masa Depan Hutan Tropis Dunia, Langkah Baru Memimpin Konservasi
BRICS terus memperluas keanggotaannya dengan mengundang negara-negara seperti Iran, Arab Saudi, Mesir, Malaysia, dan Indonesia. Langkah ini mencerminkan upaya untuk menciptakan tatanan dunia multipolar yang lebih seimbang dan mengurangi dominasi Barat, khususnya Amerika Serikat, dalam sistem keuangan dan politik global.
Pada KTT BRICS ke-15 di Johannesburg, Agustus 2023, enam negara diundang untuk bergabung, dengan keanggotaan efektif mulai 1 Januari 2024, yaitu: Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Ethiopia.
Namun, Arab Saudi menunda keputusannya dan hingga April 2024 masih mempertimbangkan keanggotaan penuh.
Sementara itu, Indonesia secara resmi menjadi anggota penuh BRICS pada Januari 2025, setelah proses aplikasi yang dimulai pada 2023.
Baca Juga: Ancaman Sunyi di Balik Evakuasi Warga Gaza Berkedok Kemanusiaan
Ekspansi BRICS mencerminkan pergeseran menuju tatanan dunia yang lebih multipolar, di mana negara-negara berkembang memainkan peran yang lebih signifikan dalam menentukan arah kebijakan global.
Maroko dan Sudan
Abraham Accord 2020, disusul negara di kawasan Afrika mengikuti jejak kedua negara itu, yaitu Maroko dan Sudan.
Normalisasi hubungan Maroko dan Sudan dengan Israel pada periode 2020–2021 merupakan bagian dari Abraham Accords yang diprakarsai oleh Amerika Serikat.
Baca Juga: Ketika Pelukan Anak Jadi Obat Lelah
Keputusan kedua negara tersebut tidak lepas dari tekanan diplomatik dan insentif strategis dari AS, termasuk penghapusan sanksi, bantuan ekonomi, dan dukungan politik.
Insentif utama bagi Maroko adalah pengakuan resmi AS terhadap klaim kedaulatan Maroko atas Sahara Barat, wilayah sengketa dengan kelompok Polisario yang didukung Aljazair.
Imbalan AS yang menjanjikan bantuan ekonomi dan dukungan militer, termasuk akses ke peralatan militer canggih, juga menjadi alasan berikutnya. Selain Israel yang juga menawarkan kerja sama dalam pertanian, teknologi, dan keamanan.
Posisi Sudan lain lagi, negara ini mendapatkan insentif utama berupa penghapusan dari daftar negara sponsor terorisme AS, yang menjadi syarat untuk mengakses pinjaman internasional dan bantuan dari IMF serta Bank Dunia.
Kondisi krisis ekonomi Sudan setelah kejatuhan Omar al-Bashir tahun 2019, pada pemerintahan transisi tentu sangat membutuhkan bantuan ekonomi luar negeri.
Tentu saja, Sudan telah lama menjadi target sanksi ekonomi dan embargo senjata dari AS dan PBB. Pemerintah transisi sangat bergantung pada dukungan politik dan ekonomi Barat.
Di sini, normalisasi Maroko dan Sudan terhadap Israel, menunjukkan bagaimana AS menggunakan leverage politik dan ekonomi untuk mendorong agenda geopolitik di Timur Tengah dan Afrika Utara.
Yordania, Mesir dan Turkiye
Hal itu menambah deretan negara mayoritas berpenduduk Muslim yang sudah lebih dulu menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, yaitu Yordania tahun 1994 dan Mesir tahun 1979. Bahkan jauh sebelumnya, Turkiye sudah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tahun 1949.
Normalisasi hubungan Yordania dengan Israel pada tahun 1994 melalui Perjanjian Damai Wadi Araba merupakan hasil dari berbagai faktor strategis, politik, dan ekonomi. Memang benar bahwa Yordania menghadapi keterbatasan sumber daya dan tekanan geopolitik, namun keputusan tersebut lebih kompleks dari sekadar “paksaan Barat.”
Yordania menjadi negara Arab kedua setelah Mesir yang menjalin perdamaian resmi dengan Israel, melalui Treaty of Peace Between the State of Israel and the Hashemite Kingdom of Jordan yang ditandatangani pada 26 Oktober 1994 di Wadi Araba.
Tentu saja saat itu, Amerika Serikat sangat aktif menengahi perjanjian ini, dan menjanjikan bantuan ekonomi serta militer kepada Yordania.
Setelah perjanjian ditandatangani, AS meningkatkan bantuannya ke Yordania, termasuk kerja sama militer dan pinjaman lunak. AS juga menggunakan pengaruhnya di IMF dan Bank Dunia untuk mendukung pemulihan ekonomi Yordania.
Kondisi ekonomi Yordania sendiri termasuk dalam kategori rentan, dengan minimnya sumber daya alam (hampir tidak ada minyak), sangat bergantung pada bantuan luar negeri dan remitansi.
Belum lagi pada awal 1990-an, Yordania mengalami krisis ekonomi, termasuk utang luar negeri yang tinggi dan inflasi.
Normalisasi dengan Israel yang disponsori AS dipandang membantu membuka akses ke bantuan internasional dan investasi asing.
Terlebih dari sisi keamanan dan stabilitas wilayah, Yordania yang memiliki batas langsung dengan Israel dan Tepi Barat (Palestina), berusaha menghindari konflik bersenjata, mengatur isu pengungsi Palestina (Yordania memiliki populasi besar keturunan Palestina), dan menjamin keamanan air dari Sungai Yordan.
Yordania juga mendapatkan peran aktif dalam pengelolaan situs-situs suci di Yerusalem, yang merupakan kepentingan keagamaan dan politik penting, khususnya Masjid Al-Aqsa di Yerusalem.
Namun, hubungan diplomatik dengan Israel tersebut disikapi dingin di tingkat masyarakat, dengan banyak warga Yordania menolak normalisasi karena kuatnya solidaritas dengan Palestina.
Satu negara lagi, yaitu Turkiye, yang menjadi negara mayoritas Muslim pertama yang mengakui kedaulatan Israel. Langkah tersebut diambil di bawah pemerintahan Presiden İsmet İnönü, dalam konteks Turkiye sebagai negara sekuler yang didirikan oleh Mustafa Kemal Atatürk tahun 1923, dengan dukungan dari negara-negara Barat, termasuk Inggris.
Di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdoğan, hubungan Turkiye-Israel mengalami pasang surut. Pada awal masa jabatannya, Erdoğan berupaya memperkuat hubungan dengan Israel, termasuk kunjungan resmi pada 2005. Namun, insiden serangan terhadap kapal Mavi Marmara pada 2010, yang menewaskan sembilan aktivis pro-Palestina asal Turki, menyebabkan ketegangan serius. Turki menuntut permintaan maaf dari Israel, kompensasi bagi korban, dan pencabutan blokade Gaza sebagai syarat normalisasi hubungan.
Meskipun terjadi ketegangan, hubungan diplomatik mulai membaik pada 2016 dengan kesepakatan untuk memulihkan hubungan, termasuk pengembalian duta besar dan kerja sama ekonomi. Namun, ketegangan kembali muncul pada 2018 setelah AS memindahkan kedutaannya ke Yerusalem, yang menyebabkan Turki menarik duta besarnya dari Israel.
Pada Agustus 2022, Turki dan Israel sepakat untuk memulihkan hubungan diplomatik sepenuhnya, termasuk pengangkatan kembali duta besar dan konsul jenderal. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan stabilitas regional dan kerja sama ekonomi.
Namun, meskipun terjadi normalisasi, Presiden Erdoğan tetap vokal dalam mendukung Palestina dan mengkritik kebijakan Israel, terutama terkait konflik di Gaza. Pada 2024, Erdoğan mengintensifkan retorika anti-Israel, termasuk menyebut Israel sebagai “negara teroris” dan membandingkan Perdana Menteri Netanyahu dengan Hitler. Langkah-langkah ini dianggap sebagai upaya untuk memperkuat dukungan domestik di tengah krisis ekonomi dan menurunnya popularitas Erdoğan.
Pemetaan Geopolitik Timteng
Kembali ke kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Arab Saudi, di hadapan Putra Mahkota Mohammed Bin Salman, Trump mengatakan, “Ini akan menjadi hari istimewa di Timur Tengah, dengan seluruh dunia menyaksikan, ketika Arab Saudi bergabung dengan kita, dan Anda akan sangat menghormati saya dan Anda akan sangat menghormati semua orang yang telah berjuang keras untuk Timur Tengah.”
Trump sedang memperkenalkan pendekatan geopolitik baru yang menandai pergeseran signifikan dalam kebijakan AS di kawasan tersebut. Dengan mengunjungi Arab Saudi, bertemu dengan Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa, dan melanjutkan perjalanan ke Qatar, tanpa singgah di Israel atau bertemu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Trump menunjukkan rencananya untuk merancang ulang dinamika regional tanpa keterlibatan langsung Israel.
Melalui pendekatan ke Suriah, Trump rupanya ingin mengurangi pengaruh Iran dan Rusia di kawasan tersebut. AS juga bermaksud membuka peluang bagi perusahaan AS dalam proses rekonstruksi negara tersebut, bersaing dengan rencana proyek China.
Trump tidak mengunjungi Israel selama tur tersebut dan tidak mengadakan pertemuan dengan Netanyahu. Sebaliknya, ia mengkritik keras serangan militer Israel di Gaza dan menunjukkan ketidaksenangannya terhadap pendekatan Netanyahu yang dianggap menghambat upaya perdamaian. Meskipun demikian, Trump tetap menyatakan bahwa kebijakan Timteng-nya akan menguntungkan Israel dalam jangka panjang.
Di Qatar pun Trump menandatangani kesepakatan bisnis dan pertahanan besar dengan Qatar, termasuk pembelian 160 pesawat Boeing oleh Qatar Airways. Langkah ini menunjukkan upaya Trump untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara Teluk.
Strategi Trump di Timur Tengah mencerminkan upaya untuk merancang ulang tatanan geopolitik kawasan dengan mengurangi ketergantungan pada Israel dan memperkuat hubungan dengan negara-negara Arab. Meskipun pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas dan membuka peluang ekonomi, banyak pihak menilai bahwa kebijakan tersebut justru akan menuai kontroversial dan berisiko memperburuk ketegangan regional.
Pelanggaran Konsensus Arab
Keputusan sejumlah negara Arab untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, terutama tahun 2020, dan yang sekarang sedang didesak Trump, secara langsung sesungguhnya btelah melanggar konsensus kolektif yang telah dipegang selama dua decade oleh Negara-negara Arab sendiri. Konsesnsus menyatakan bahwa pembentukan negara Palestina adalah syarat utama bagi normalisasi dengan Israel.
Langkah-langkah sepihak ini dianggap oleh banyak kalangan sebagai bentuk normalisasi tanpa keadilan, dan justru melemahkan posisi Palestina dalam negosiasi dan memberikan legitimasi terhadap pendudukan Israel tanpa syarat.
Konsensus Inisiatif Perdamaian Arab 2002 yang diadopsi oleh Liga Arab di Beirut, antara lain menyatakan bahwa normalisasi penuh dengan Israel oleh seluruh negara Arab, dengan catatan sebagai imbalannya, Israel harus menarik diri dari wilayah pendudukan 1967 (Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur) serta menyetujui pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
Justru walaupun normalisasi sudah dijalankan, ternyata tanpa ada kemajuan nyata dalam pembentukan negara Palestina. Malah Israel terus memperluas permukiman ilegal di Tepi Barat, masih memblokade dan malah menyerang Gaza sejak Oktober 2023, dan menolak status Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina, malah memindahkan pusat pemerintahannya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Termasuk memindahkan kedutaan-kedutaan besar negara-negara yang pro-Israel ke Yerusalem.
Apa Keuntungan Bagi Palestina?
Pada pelaksanaan Abraham Accord tahun 2020, pemerintah Palestina dan berbagai faksi seperti Hamas dan Fatah mengecam normalisasi negara-negara Arab tersebut sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina.
Beberapa negara Arab seperti Aljazair, Irak, dan Tunisia menolak keras normalisasi dan tetap mempertahankan sikap berdasarkan Inisiatif Arab.
Di tingkat rakyat, banyak warga di negara-negara Arab menolak normalisasi, meskipun pemerintah mereka melakukannya demi keuntungan strategis atau ekonomi.
Kini, kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Arab Saudi dan Qatar, serta bertemu Suriah, mendapat tanggapan keras dari pihak Palestina.
Meskipun Trump menyatakan niatnya untuk mendukung rakyat Palestina, tetap saja tidak memberikan keuntungan nyata bagi Palestina. Justru sebaliknya, rencana tersebut menimbulkan kekhawatiran akan pelanggaran hak asasi manusia dan memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza.
Palestina sangat mengkhawatirkan bahwa beberapa negara Arab telah menormalisasi hubungan dengan Israel tanpa menunggu terbentuknya negara Palestina yang merdeka dan beraulat, yang telah melanggar konsensus Arab sebelumnya.
Namun demikian, Palestina tetap berkomitmen untuk memperjuangkan hak-haknya melalui diplomasi internasional dan dukungan dari masyarakat global, serta melalui gerakan perlawanan.
Walaupun Trump ke Arab tanpa mampir ke kawannya, Netanyahu, itu hanya main mata saja. Tetap saja proyeksinya adalah memberikan panggung, tempat dan posisi kepada Israel sebagai kepanjangan tangan pengaruh kawasan geopolitik AS di Timur Tengah sebagai representatsi dunia Islam, dan barometer penguasaan pengaruh dunia secara gobal.
Di sini negara-negara Arab harus waspada akan rancana strategi Trump AS, yang dapat merugikan perjuangan Palestina dan kawasan Tmur Tengah sendiri. []
Mi’raj News Agency (MINA)
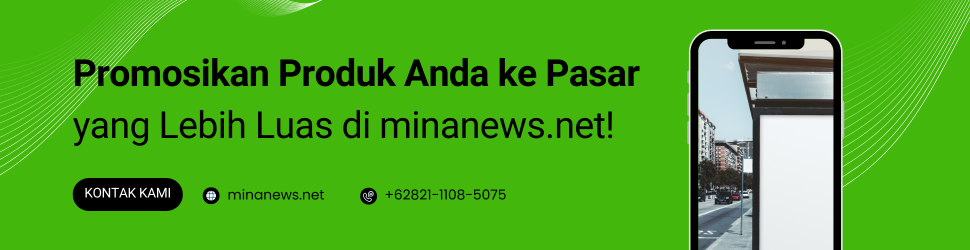


























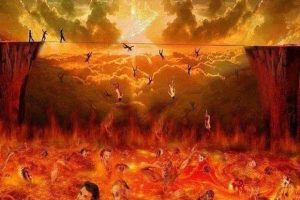
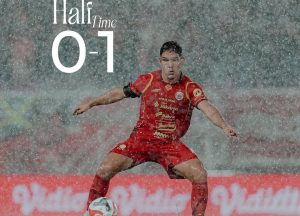
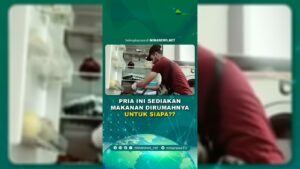



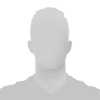
 Mina Indonesia
Mina Indonesia Mina Arabic
Mina Arabic Mina Preneur
Mina Preneur