Oleh Ali Farkhan Tsani, Duta Al-Quds Internasional
Perjuangan rakyat dan bangsa Palestina untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan zionis tak akan pernah benar-benar kuat jika terus diiringi dengan konflik internal Palestina itu sendiri.
Faksi-faksi Palestina seperti Hamas, Fatah, Jihad Islam, dan lainnya, meski berbeda strategi dan pendekatan, sejatinya memiliki musuh yang sama yakni penjajahan Zionis, dan tujuan sama yaitu kemerdekaan negara Palestina yang berdaulat sepenuhnya.
Namun selama ini, perbedaan politik, ideologi, dan kepentingan lokal telah menjadi penghalang utama untuk membentuk satu front perjuangan nasional yang utuh. Perpecahan tersebut hanya melemahkan posisi Palestina di mata internasional, menyulitkan diplomasi, dan memberi ruang bagi pendudukan Zionis untuk terus memecah belah dan mendikte peta perlawanan.
Baca Juga: Bulan Solidaritas Terhadap Rakyat Palestina
Perbedaan mendasar antara Fatah dan Hamas, juga faksi perlawanan lainnya terletak pada strategi perjuangan, ideologi, dan pendekatan terhadap pendudukan Zionis.
Dalam strategi perjuangan misalnya, Fatah lebih mengedepankan diplomasi dan negosiasi politik, mendukung solusi dua negara dan terlibat dalam proses perjanjian demi perjanjian.
Namun fakta di lapangan membuktikan bahwa perjanjian demi perjanjian yang ditempuh faksi Fatah, terutama melalui jalur diplomasi dan negosiasi dengan Zionis, justru tidak menghentikan penjajahan, melainkan malah memperkuat posisi Zionis di atas wilayah Palestina.
Beberapa fakta penting menunjukkan hal itu. Terutama Perjanjian Oslo (1993–1995), yang isinya bahwa Fatah dan Zionis sepakat untuk membentuk Otoritas Palestina dan mengatur kawasan tertentu. Namun, hasilnya ekspansi permukiman ilegal Zionis justru meningkat drastis, dan status Yerusalem tetap tidak diakui sebagai ibu kota Palestina.
Baca Juga: Menetapi Jama’ah, Menjaga Diri dari Zaman Penuh Luka
Fakta di lapangan juga menunjukkan kondisi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, meskipun menjadi bagian dari wilayah Palestina menurut peta PBB, tapi 85% lebih wilayah tersebut dikuasai dan dikontrol penuh oleh Zionis.
Masjidil Aqsa pun terus mengalami penyerbuan, aksi provokatif dan yahudisasi, yang merupakan pelanggaran atas status quo yang sudah disepakati.
Padahal Fatah pada awal berdirinya adalah gerakan perlawanan bersenjata, bukan gerakan diplomasi seperti sekarang.
Fatah (Harakah at-Tahrir al-Wathani al-Filasthini atau Gerakan nasional Pembebasan Palestina), adalah partai politik yang didirikan 1958 oleh sekelompok pejuang Palestina di pengasingan, saat itu berpusat di Kuwait, termasuk Yasser Arafat.
Baca Juga: Dialog dan Experiential Learning Pada Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidr
Visi awal pendirian Fatah adalah pembebasan penuh Palestina melalui perjuangan bersenjata (revolusioner).
Hal itu dilaksanakan ketika tahun 1965, Fatah meluncurkan serangan bersenjata pertamanya terhadap pendudukan Zionis. Aksi tersebut dikenal sebagai awal perlawanan bersenjata Palestina modern.
Fatah kemudian menjadi inti dari PLO (Palestine Liberation Organization atau Organisasi Pembebasan Palestina) dan Arafat menjadi simbol perlawanan rakyat Palestina.
Namun terjadi arah perubahan, hingga pada tahun 1988, PLO mulai mengakui resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan keberadaan pendudukan Zionis secara tidak langsung.
Baca Juga: 14 Poin Krusial KUHAP Baru, Publik Soroti Risiko Pelemahan Hak Asasi
Hingga pada Perjanjian Oslo (1993) menjadi titik balik besar, ketika Fatah membentuk Otoritas Palestina, dan konsekwensinya mengurangi orientasi perjuangan bersenjata. Sejak saat itu, Fatah lebih fokus pada kekuasaan administratif daripada perlawanan.
Kekecewaan terhadap jalur diplomasi yang ditempuh Fatah tahun 80-an, yang dinilai gagal mewujudkan kemerdekaan Palestina, itu menjadi salah satu latar belakang berdirinya Hamas.
Munculnya Gerakan Perlawanan Hamas
Hamas (Harakah Muqawwamah al-Islamiyah atau Gerakan Perlawanan Islam) didirikan pada Desember 1987. Seiring dengan munculnya Intifada Pertama, pemberontakan rakyat Palestina melawan penjajahan pendudukan Zionis.
Baca Juga: Indonesia dan Masa Depan Hutan Tropis Dunia, Langkah Baru Memimpin Konservasi
Melihat penindasan pendudukan Zionis yang terus-menerus, dan kegagalan diplomasi PLO, Hamas memutuskan untuk turun ke jalur perlawanan langsung.
Hamas menolak pengakuan terhadap pendudukan Zionis, dan menyerukan pembebasan total tanah Palestina. Maka, Hamas fokus pada perlawanan bersenjata (muqawamah) dan juga kesejahteraan rakyat dengan membangun sekolah, klinik, dan layanan sosial.
Langkah-langkah perlawanan bersenjata dan juga kesejahteraan rakyat yang dilakukan Hamas, rupanya mendapat simpati besar dari rakyat Palestina. Ini terbukti aksi-aksi perlawanan di lapangan yang selalu diikuti rakyat bahkan anak-anak muda Intifadah.
Hingga dampaknya terlihat pada kontestasi Pemilu Legislatif Palestina tahun 2006, yang dimenangkan oleh Hamas, dan Hamas berhak mengendalikan pemerintahan Palestina. Pada sisi lain, Fatah yang kalah tidak menerima hasil secara utuh, dan ketegangan pun mulai memuncak.
Baca Juga: Ancaman Sunyi di Balik Evakuasi Warga Gaza Berkedok Kemanusiaan
Pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh pun diangkat sebagai Perdana Menteri Palestina pada 29 Maret 2006, setelah Hamas menang dalam pemilu legislatif yang demokratis.
Ismail Haniyeh disahkan oleh Presiden Mahmoud Abbas (Fatah), sesuai hasil pemilu demokratis Palestina Januari 2006. Pada Pemilu saat itu, Hamas menang 76 dari 132 kursi di Dewan Legislatif.
Ismail Haniyeh setelah pelantikannya, sempat membentuk Kabinet yang didominasi oleh tokoh-tokoh Hamas, terutama untuk jabatan-jabatan strategis. Di antaranya: Menteri Luar Negeri dipegang oleh Mahmoud al-Zahar (Tokoh senior Hamas), Menteri Dalam Negeri dijabat oleh Said Siyam (Meninggal dalam serangan Zionis 2009), Menteri Keuangan dijabat Omar Abdel Razek (Ekonom Hamas, ditangkap Israel 2006), Menteri Pekerjaan Umum dipegang Issa al-Jabari (Tokoh lokal Hamas di Hebron), dan sebagainya.
Namun nasib Kabinet Haniyeh hanya berlangsung sekitar satu tahun. Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Israel menolak mengakui kabinet Hamas, karena dianggap tidak mengakui eksistensi Israel dan menolak Perjanjian Oslo. Barat malah menyebutnya sebagai “teroris”. Dana Pajak Palestina pun ditahan pendudukan Zionis, yang menyebabkan krisis ekonomi.
Baca Juga: Ketika Pelukan Anak Jadi Obat Lelah
Sementara di lapangan terjadi krisis politik antara Hamas dan Fatah yang memuncak pada Juni 2007, setelah bentrokan bersenjata di Gaza.
Melihat situasi itu, Presiden Mahmoud Abbas memecat Ismail Haniyeh dari jabatan Perdana Menteri, membubarkan Kabinet, dan membentuk pemerintahan darurat yang berbasis di Tepi Barat.
Setelah memecat Haniyeh, Presiden Abbas mengangkat Dr. Salam Fayyad sebagai Perdana Menteri Palestina. Fayyad pun segera membentuk pemerintahan darurat yang berkedudukan di Tepi Barat.
Namun, meskipun secara resmi diberhentikan, Haniyeh tetap memimpin pemerintahan Palestina secara de facto di Jalur Gaza sejak 2007.
Baca Juga: Kritik Radikal Ilan Pappe terhadap Proyek Kolonial Israel
Sejak itulah Palestina terbelah dua: Hamas (Haniyeh) menguasai Gaza dan Fatah (Abbas) menguasai Tepi Barat.
Perkembangan berikutnya, tahun 2017, Ismail Haniyeh ditetapkan menjadi Kepala Biro Politik Hamas, menggantikan Khaled Meshaal. Haniyeh tetap menjadi tokoh sentral Hamas dan politik Palestina hingga kesyahidannya pada 31 Juli 2024 dini hari di Teheran, Iran, oleh serangan rudal, yang diduga kuat atas peran intelijen Zionis.
Tuntutan Rekonsiliasi
Perbedaan garis politik yang rentan mengarah pada konflik dan perpecahan tentu saja berdampak pada hambatan perjuangan kemerdekaan Palestina, memperlemah posisi tawar di dunia internasional, dan itu dimanfaatkan oleh Zionis untuk terus memecah-belah.
Baca Juga: Pentingnya Narasi dan Literasi dalam Perjuangan Palestina
Seiring waktu, kondisi di lapangan, dan tuntutan rakyat untuk kemerdekaan Palestina, serta dukungan kuat negara-negara di dunia, maka berbagai upaya rekonsiliasi mulai dilakukan, walaupun belum tuntas hingga saat ini.
Langkah-langkah strategis rekonsiliasi Hamas, Fatah dan faksi-faksi perjuangan Palestina lainnya, mestilah didasari pada keinginan membangun agenda bersama dengan fokus pada tujuan utama, yaitu pembebasan Palestina dari penjajahan Zionis.
Semua faksi juga harus sepakat bahwa kepentingan nasional harus lebih tinggi daripada kepentingan faksi atau kelompok. Faksi-faksi juga harus secara bersama membangun Pemerintahan Persatuan Nasional yang diisi oleh perwakilan dari semua faksi, kalangan profesional dan independen.
Selain itu, Mahmoud Abbas (89 th) juga telah lama menjabat sebagai Presiden Otoritas Palestina sejak 15 Januari 2005, menggantikan Yasser Arafat yang wafat pada 2004. Lamanya berkuasa, sudah lebih dari 19 tahun menjabat (2005–2025), sementara masa jabatan seharusnya hanya per 4 tahun, membuat kepemimpinan Abbas terlihat rapuh, seperti tak berdaya dan terlalu lemah menghadapi pendudukan Zionis.
Baca Juga: Ternyata Jadi Ayah Tak Seindah Cerita Film
Fakta di lapangan membuktikan kepemimpinan Mahmoud Abbas kehilangan legitimasi di mata banyak rakyat Palestina, terutama generasi muda, dan tidak memiliki kontrol atas Jalur Gaza, yang dikuasai Hamas sejak 2007. Di Tepi Barat pun, otoritasnya sangat terbatas, karena banyaknya wilayah yang diduduki dan dikuasai penuh oleh militer Zionis dan permukiman Yahudi.
Yang lebih memprihatinkan lagi, Otorita Palestina berjalan tanpa kekuatan militer alias tidak memiliki angkatan bersenjata layaknya sebuah negara. Otoritas Palestina hanya memiliki pasukan keamanan internal, tanpa kekuatan militer sejati. Koordinasi keamanan dikendalikan sepenuhnya oleh Zionis yang tentu lebih mengamankan kepentingan Zionis daripada rakyat Palestina.
Dari sisi keuangan, tak kalah gentingnya. Pemerintah Palestina sangat-sangat bergantung pada bantuan luar negeri, terutama dari Barat dan negara-negara Arab. Di sisi lain, Otoritas Zionis sering menahan pendapatan pajak milik Otoritas Palestina, yang ini memperburuk krisis fiskal Palestina.
Jadi, tidak bisa dipungkiri, faktor usia, kompleksitas permasalahan, Mahmoud Abbas memimpin sejak 2005, kini kekuasaannya melemah drastis secara politik, militer, dan ekonomi. Maka, tuntutan Pemilu demokratis legislatif dan presiden Palestina yang adil, bebas, dan diawasi internasional, menjadi keniscayaan. Hasilnya pun nanti harus diakui bersama, tak diulang seperti krisis pasca pemilu 2006.
Setelah itu, diperkuat dengan koordinasi perlawanan dan diplomasi yang seiring sejalan secara integral. Hamas dan faksi perlawanan bersenjata bisa fokus mengorganisasi resistensi terkontrol dan terukur. Sementara Fatah dan PLO memaksimalkan diplomasi internasional. Semua pihak bisa saling melengkapi, bukan saling menegasikan.
Reformasi PLO juga menjadi strategis, yaitu dengan memasukkan unsur Hamas dan faksi lainnya secara resmi ke dalam struktur PLO sebagai payung politik seluruh rakyat Palestina. Maka, rekonsiliasi antara Hamas, Fatah, dan faksi-faksi lain di Palestina menjadi sangat mungkin, tapi membutuhkan kemauan politik, keikhlasan, dan kesadaran bersama bahwa persatuan adalah syarat utama kemerdekaan.
Padahal sudah banyak pertemuan-pertemuan rekonsiliasi faksi-faksi Palestina di luar Palestina. Sebut saja pertemuan rekonsiliasi di Makkah (2007), Kairo (2011 dan 2017), Doha (2012 dan 2016), Istanbul (2020), Aljazair (Oktober 2022) hingga Beijing (2024). Indonesia diharapkan sebagai tuan rumah pada waktu berikutnya.
Terkini, rekonsiliasi di China, 21-23 Juli 2024, yang dihadiri 14 faksi Palestina sepakat untuk mengakhiri perpecahan mereka dan memperkuat persatuan Palestina. Penandatangan deklarasi Beijing juga disaksikan utusan atau perwakilan dari mancanegara, yaitu: Mesir, Aljazair, Arab Saudi, Qatar, Yordania, Suriah, Lebanon, Rusia, dan Turki.
Ada beberapa poin Deklarasi Beijing yang sangat penting dan mendasar, di antaranya: Pembentukan Pemerintahan Rekonsiliasi Nasional Sementara. Pada poin ini, para faksi sepakat membentuk pemerintahan sementara yang akan mengelola rekonstruksi Gaza pascaperang dan mempersiapkan pemilihan umum nasional secepat mungkin sesuai dengan hukum yang berlaku.
Poin lainnya, Komitmen terhadap Negara Palestina Merdeka. Deklarasi menegaskan kembali komitmen untuk mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem (Al-Quds) sebagai ibu kotanya, sesuai dengan resolusi-resolusi PBB yang relevan.
Termasuk perlunya Reformasi dan Integrasi Institusi Politik. Dalam hal ini, faksi-faksi sepakat untuk membentuk Dewan Nasional Palestina yang baru dan mengaktifkan kerangka kepemimpinan terpadu sementara, yang akan berfungsi secara institusional untuk pengambilan keputusan politik bersama.
Lagi-lagi, deklarasi masih di atas kertas. Meskipun Deklarasi Beijing merupakan langkah signifikan menuju persatuan Palestina, implementasinya menghadapi tantangan besar.
Tantangan tersebut berupa: Ketidakpercayaan antara faksi-faksi yang telah lama bersaing, tekanan eksternal dari negara-negara yang menentang keterlibatan Hamas dalam pemerintahan, serta kondisi kemanusiaan dan infrastruktur yang rusak parah di Gaza, yang memerlukan perhatian segera.
Keberhasilan rekonsiliasi akan sangat bergantung pada komitmen nyata dari semua faksi untuk bekerja sama dan mengatasi perbedaan demi kepentingan rakyat dan bangsa Palestina. Tidak ada jalan lain, persatuan adalah jalan satu-satunya. Selama Palestina terpecah, penjajah akan terus menguasainya.
Sudah waktunya faksi-faksi Palestina belajar dari kesalahan masa lalu, dan duduk bersama untuk kemerdekaan bangsanya, bukan untuk kekuasaan faksinya masing-masing.
Jika kekuatan diplomasi, perlawanan, dan solidaritas rakyat disatukan, dunia akan kembali melihat bahwa kemerdekaan Palestina bukan sekadar mimpi, tapi keniscayaan yang diperjuangkan bersama.
Jika Palestina bersatu, Zionis akan gemetar. Karena Persatuan adalah kekuatan, sedangkan perpecahan adalah kehancuran. []
Mi’raj News Agency (MINA)






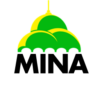




























 Mina Indonesia
Mina Indonesia Mina Arabic
Mina Arabic Mina Preneur
Mina Preneur