DI ZAMAN ketika segalanya diukur dengan angka, ranking, biaya, dan profit, pendidikan—yang dulu menjadi cahaya peradaban—perlahan kehilangan sinarnya. Lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi tempat menempa akhlak, menumbuhkan kebijaksanaan, serta membentuk pribadi yang utuh, kini mulai tergelincir menjadi “lumbung cuan” yang sibuk menghitung pemasukan.
Pembangunan gedung megah diutamakan, sementara pembangunan jiwa terlupakan. Program-program pendidikan disulap menjadi komoditas, bukan lagi amanah. Di tengah gegap gempita promosi “unggulan”, kita justru kehilangan inti: pendidikan yang mendidik manusia, bukan hanya pasar yang menjual jasa belajar.
Banyak sekolah hari ini lebih sibuk mengejar akreditasi daripada mengakreditasi diri mereka pada nilai-nilai yang benar. Mereka berlomba mempercantik brosur, bukan memperbaiki kedalaman ajarannya. SPP naik, biaya bangunan melambung, sementara kualitas pengasuhan tidak berbanding lurus. Anak-anak diperlakukan seperti pelanggan, bukan amanah yang harus dibentuk. Padahal, seorang murid bukanlah mesin pencetak nilai ujian, melainkan manusia yang sedang bertumbuh dengan segala potensi dan kelemahannya.
Di pesantren, fenomena yang mirip mulai tampak. Di tempat yang seharusnya menjadi pusat tazkiyatun nafs, pusat penyucian jiwa dari dunia yang penuh hiruk-pikuk, kini muncul program-program tambahan yang lebih mirip layanan jasa. Fokus pada hafalan tanpa pembinaan akhlak yang kokoh. Santri yang menghafal 30 juz dipuji setinggi langit, tetapi akhlaknya terabaikan, sifat tawadhu memudar, dan bekal adab tidak diprioritaskan.
Baca Juga: Dua Santri Shuffah Al-Jama’ah Ikuti International Student Exchange di Thailand
Pesantren yang dulunya sederhana dan penuh wibawa kini terhimpit oleh tuntutan pasar: “bagaimana biayanya?”, “berapa fasilitasnya?”, “apa keunggulannya di brosur?”. Seakan-akan kualitas pengajaran agama diukur dari berapa besar gedungnya dan seberapa mahal biaya masuknya. Ironis, namun nyata.
Tentu tidak semua sekolah dan pesantren seperti itu. Masih banyak lembaga mulia yang tulus menjaga amanah pendidikan. Tetapi fakta-fakta lapangan tidak bisa kita tutupi: banyak yang tergelincir dalam arus kapitalisasi pendidikan.
Guru yang mengajar dengan gaji rendah dipaksa tampil sempurna, sementara para pemilik lembaga hidup nyaman dengan seragam bisnis yang rapi. Orang tua dibebani macam-macam biaya atas nama “pengembangan”, padahal yang berkembang seringkali hanya kas institusi. Sementara karakter anak? Tetap rapuh, mudah goyah, dan miskin nilai.
Pendidikan yang Hilang Arah
Baca Juga: Anak Hebat Lahir dari Lingkungan yang Mendukung
Arah pendidikan berubah. Murid dituntut menjadi hebat dalam matematika, sains, teknologi, tapi tidak hebat dalam memanusiakan manusia. Mereka pintar berkompetisi, namun lemah berempati. Sekolah mendorong prestasi akademik, tetapi tidak mendorong anak untuk tahu cara meminta maaf, menghormati orang tua, menjaga lisan, atau menahan diri dari keburukan. Mereka diajari cara memenangkan lomba, tapi tidak diajari cara menang melawan hawa nafsu.
Di pesantren, hafalan banyak, tetapi memahami makna kehidupan sedikit. Santri bisa membaca kitab, tapi tidak semua terbiasa beradab kepada gurunya. Banyak yang fasih melantunkan ayat, namun tidak membumikan ayat tersebut dalam perilakunya.
Fasilitas pesantren berkembang, bangunan bertingkat berdiri, tetapi kedalaman ruhiyah tidak ikut naik. Semua serba tergesa, yang penting “ada jualannya”, “ramai pendaftarnya”, dan “keuntungannya lumayan”.
Padahal inti dari pendidikan adalah membentuk manusia. Bukan menjual paket pelajaran. Bukan membangun gedung megah. Bukan menampilkan brosur indah. Pendidikan adalah proses panjang menumbuhkan kejujuran, melatih tanggung jawab, menumbuhkan empati, mengasah keteguhan hati, dan membimbing generasi agar dekat dengan Tuhannya. Ini pekerjaan hening, perlahan, tidak megah, tidak glamor. Tetapi justru di situlah keagungannya.
Baca Juga: Belajar Sabar dari Anak Sendiri
Namun kini, keheningan itu tertutup oleh suara kasir pembayaran, oleh rapat anggaran, oleh proposal sponsorship, oleh target pemasukan tahunan. Pendidikan semakin mirip industri. Murid satu per satu berubah menjadi “nomor pembayaran”.
Bahkan ada yang tidak diterima hanya karena orang tuanya kurang mampu, padahal siapa tahu anak itu kelak menjadi cahaya bagi umat? Pendidikan kehilangan rasa iba, kehilangan kemanusiaan, kehilangan misi profetik.
Di titik ini, kita perlu bertanya dengan jujur: untuk siapa sekolah dan pesantren itu dibangun? Untuk mencetak manusia atau mencetak keuntungan? Untuk menegakkan adab atau menegakkan bisnis? Untuk membesarkan hati murid atau membesarkan laporan keuangan?
Jika semua pihak—guru, ustadz, pengurus, yayasan, dan orang tua—berani kembali merenung, mungkin kita masih punya harapan. Pendidikan akan kembali ke jalan lurusnya ketika akhlak menjadi pondasi, bukan bonus. Ketika guru dihormati karena keteladanannya, bukan karena target kurikulumnya.
Baca Juga: Belajarlah Bahagia dengan Hal-Hal Sederhana
Ketika pesantren menjadi tempat menempa jiwa, bukan tempat memasarkan fasilitas. Ketika murid diperlakukan sebagai amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, bukan sebagai pelanggan yang harus dimaksimalkan nilainya.
Saat sekolah dan pesantren berhenti menjadi lumbung cuan, pada saat itulah pendidikan akan kembali menemukan jiwanya. Dan mungkin, generasi yang tumbuh sesudah itu akan lebih jujur, lebih beradab, lebih kuat, dan lebih dekat kepada kebenaran. Semoga kita tidak terlambat menyadarinya.[]
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Anak yang Didengar, Tumbuh Lebih Bahagia
















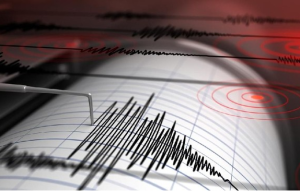

















 Mina Indonesia
Mina Indonesia Mina Arabic
Mina Arabic Mina Preneur
Mina Preneur