DALAM terik matahari yang membakar, saya tiba di Desa Awe Geutah, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Kabupaten Bireuen, Aceh. Suhu siang itu mencapai 27 derajat Celsius, namun rasa penasaran membawa saya kembali mengunjungi makam dan rumah peninggalan ulama besar, Teungku Chik di Awe Geutah.
Kunjungan ini adalah kali kedua. Sayangnya, juru kunci yang juga ahli waris, Teungku Muhsin, tidak ada di tempat. Sebelumnya, saya sempat bertemu Cut ‘Ati, seorang nenek yang juga ahli waris. Namun, usia membuat ingatannya tentang sang ulama dan peninggalannya mulai memudar.
Dari gapura bertuliskan “Makam Teungku Chik di Awe Geutah,” suasana kompleks langsung terasa khas Aceh. Rumah panggung berdiri kokoh dengan tiang-tiang besar dari kayu tua yang masih kuat. Rumah ini pernah direstorasi pemerintah, meski sebagian elemen aslinya tetap dipertahankan.
Kunjungan pertama ke tempat ini, saya disambut dengan gapura yang bertuliskan Makam Teungku Chik Di Awe Geutah, persis berada di pinggir jalan yang berhadapan langsung dengan Masjid Desa Awe Geutah. Dari gapura, suasana terlihat seperti memasuki gang kecil yang umumnya terdapat di kawasan padat penduduk. Namun ternyata setelah gapura, terdapat gerbang selanjutnya dengan tulisan komplek makam Teungku Chik di Awe Geutah.
Baca Juga: Zohran Mamdani, Jejak Anak Imigran Muslim Merebut Panggung Amerika
Sekitar 100 meter dari gapura atau persis setelah gerbang komplek, terdapat Dayah Teungku Chik di Awe Geutah. Ada sekitar sepuluh balai pengajian di dalamnya. Tak jauh dari balai pengajian terlihat makam Teungku Chik di Awe Geutah.
Persis berada di bawah rumah almarhum. Di ujung komplek terdapat rumah-rumah keturunan dari Teungku Chik di Awe Geutah. Bentuk rumah-rumah di komplek ini yaitu rumah panggung. Seperti rumah Aceh pada umumnya. Dengan tiang-tiang penyangga yang begitu besar, dan kuat. Khas kayu zaman dahulu. Tiang-tiangnya masih terlihat bagus. Sebelumnya dari Cut ‘Ati, saya mengetahui bahwa rumah ini pernah di perbaiki oleh pihak pemerintah.
“Rumoh nyoe ka meuthon thon. Kaleuh geu plitur le awak kanto. Ka geulakee, kakeuh tabri ju. Meunyo hana geuplitur, kayee jih kabeh teupluek (rumah ini sudah bertahun-tahun. Sudah pernah diplitur oleh orang kantor. Sudah diminta plitur, yasudah kita beri saja. Kalau tidak di plitur, kayunya sudah rapuh),” kata Cut ‘Ati.
Di dalam kompleks ini juga terdapat sumur kalut dan rumah kalut. Sumur kalut, konon menurut warga sekitar dipercaya memiliki khasiat yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Sumur ini digembok, dan tidak sembarang orang bisa mengambil air dari sana.
Baca Juga: Mengenal Sosok Hemedti Komandan RSF dan Sudan yang Terbelah
Biasanya gembok akan dibuka jika ada warga yang ingin melepas kaoy atau bernazar. Dan hanya keturunan dari Teungku Chik di Awe Geutah yang dapat menimba air dari sumur ini.
“Biasanya kalau sakit kepala, atau sakit badan, kami ambil air ke sana. Atau misalnya bernazar supaya sembuh penyakitnya maka akan minum air dari sumur itu,” ujar Zulfahanum warga sekitar Gampong Awe Geutah.
Suasana komplek begitu teduh dengan tanaman hias yang dibentuk rapi mengelilingi rumah. Halaman lainnya dipasangi blok-blok batako, dan pekarangan ini dibatasi dengan tembok-tembok besar sebagai pagar.
Di hari kedua, saya juga masih menunggu sang ahli waris lainnya. Hingga adzan dhuhur berkumandang, sang ahli waris belum juga ada di rumah. Menurut warga sekitar Teungku Muhsin atau ahli waris Teungku Chik di Awe Geutah sedang mengaji dan baru akan pulang pukul 14.00 WIB.
Baca Juga: Hassan al-Turabi Pemikir Kontroversial dari Sudan
Setelah dua hari berturut-turut berkunjung, dan berjam-jam menunggu, akhirnya saya berkesempatan untuk bertemu dengan Teungku Muhsin, sekaligus mengetahui tentang peninggalan ulama dan sejarah dakwah yang ada di Aceh.
Dari Teungku Muhsin, saya akhirnya mengetahui bahwa rumah yang saat ini ditempatinya dan yang pertama kali kami datangi ketika bertemu dengan Cut ‘Ati merupakan bangunan kedua. Yang dibangun setelah Teungku Chik di Awe Geutah meninggal. Sedangkan rumah dasar Teungku Chiek di Awe Geutah telah dijadikan makam.
“Ini bangunan kedua. Rumah dasar Teungku Chiek di Awe Geutah telah dijadikan makam. Sehingga setiap ada yang berkunjung untuk mengetahui rumah Teungku Chiek di Awe Geutah maka akan datang kemari. Sedangkan yang ingin berziarah, maka akan langsung datang ke makam. Yang berada di depan dayah,” jelas Teungku Muhsin.
.Di sini biasanya masyarakat sekitar maupun luar berdatangan untuk berziarah, ada juga yang melakukan pelepasan kaoy atau bernazar, selain itu sebagian warga menjadikan tempat ini sebagai tempat troen tanoh aneuk. Troen tanoh aneuk atau turun tanah anak merupakan tradisi yang terkenal di Aceh. Artinya, orang tua menurunkan bayi ke tanah.
Baca Juga: Sunan Drajat: Dakwah Kasih Sayang yang Menyentuh Hati
Hal ini dilakukan sewaktu bayi berusia 44 hari. Keluarga mengharapkan agar doa-doa yang diucapkan ketika menuntun bayi menginjakkan tanah, sang bayi selalu mendapatkan kesalamatan dan perlindungan dari Allah. Sedangkan tujuannya dilakukan di tempat keramat peninggalan ulama ini dimaksudkan agar sang bayi kelak memiliki akhlak yang baik dan dapat menjadi penerus ulama yang berjuang untuk agama Allah.
Siapa Teungku Chik di Awe Geutah?
Teungku Chik Awe Geutah bernama asli Abdul Rahim bin Muhammad Saleh. Seorang ulama sufi yang berasal dari Kan’an, Iraq. Kemudian hijrah dan menetap di Awe Geutah hingga meninggal di sana. Namun tidak diketahui persis tahun berapa Abdul Rahim menginjakkan kaki ke Aceh. Di batu nisannya pun tidak tertera tahun meninggal ulama besar tersebut.
Namun jika diperhatikan melalui peninggalan kitab yang ditulis tangan, terdapat tulisan arab Fii zamani Ali Mughayatsyah, yang dapat diartikan bahwa ada di masa Ali Mughayatsyah. Sedangkan Ali Mughayatsyah ada sebelum masa Sultan Iskandar Muda. Akan tetapi terjadi pula perbedaan pendapat mengenai tahun kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Sebagian mencatat Sultan Iskandar Muda memimpin pada abad ke-8 dan sebagian lainnya mencatat abad ke-5. Sehingga tahun persis datangnya Teungku Chiek di Awe Geutah pun tidak tercatat secara pasti.
Baca Juga: Tiga Ulama, Satu Napas Keilmuan Pesantren Lirboyo
Perjalanan Abdul Rahim hijrah ke Aceh hingga menetap di Awe Geutah memiliki cerita tersendiri. Abdul Rahim hijrah bersama para sahabat dan keluarganya. Dalam riwayat disebutkan, ada sembilan ulama yang hijrah bersama Teungku Chiek di Awe Geutah ini. Hingga mendapat julukan cap sikureung atau cap sembilan. Dan kesembilannya kemudian berpencar mencari tempat tinggal dan menyebarkan agama Islam. Hingga Sembilan ulama ini memiliki julukan masing-masing sesuai tempat mereka menetap.
Pencarian untuk mendapatkan negeri yang aman dan tentram, membuat rombongan Abdul Rahim harus menyinggahi beberapa tempat. Pertama Abdul Rahim singgah di kepulauan Nicobar dan Andaman di Samudera Hindia. Kemudian singgah di Pulau Weh. Lalu ke pulau Sumatera, yang pada saat itu disebut dengan Pulau Ruja. Di pulau tersebut rombongan ini menetap beberapa saat di Gampong Lamkabeu, Aceh Besar.
Merasa belum menemukan tempat yang cocok sebagai tempat menetap, lalu rombongan Abdul Rahim, melanjutkan lagi pelayaran dan akhirnya mendarat di Kecamatan Jangka. Rombongan Abdul Rahim menetap di desa Asan Bideun. Rombongan ini tinggal beberapa waktu dan mendirikan balai pengajian untuk menyiarkan agama Islam.
Merasa tidak cocok juga dengan tempat ini, Abdul Rahim memutuskan untuk meminta petunjuk kepada Allah dengan melakukan istikharah empat malam berturut-turut, dan harus naik ke atas bukit menghadap ke empat arah penjuru mata angin. Dari empat arah mata angin, arah timurlah yang akhirnya menunjukkan tanda-tanda yaitu dengan adanya semburat cahaya dari arah sana. Maka keesokan harinya rombongan langsung menuju ke tempat di mana asal cahaya itu berada.
Baca Juga: Sunan Bonang, Sang Penuntun Jiwa yang Mengharmonikan Cahaya Islam dan Budaya Nusantara
Saat itu tempat ini masih hutan belantara. Kemudian ditebang dan dijadikannyalah perkampungan. Dari rombongan Teungku Chiek di Awe Geutah inilah, nama Awe Geutah itu ada. Yaitu ketika bergotong royong dan salah satu diantara rombongan membersihkan getah rotan yang menempel di tangan. Kemudian mengusulkan agar perkampungan ini diberi nama Awe Geutah atau getah rotan. Dan Abdul Rahim pun menyetujuinya.
Sumur Penawar: Jejak Zamzam dari Tanah Arab
Salah satu kisah yang paling menarik dari jejak Teungku Chik di Awe adalah tentang sumur kalut. Dikisahkan, Abdul Rahim membawa air zamzam dalam perjalanannya. Saat persediaan habis, ia menggali sumur dan mencampurkan sisa air zamzam ke dalamnya. Hingga kini, air sumur tersebut tak pernah kering, menjadi sumber berkah bagi masyarakat sekitar.
Saat ini sumur penawar juga dengan ie mon (air sumur) zamzam. Menurut riwayat ketika memutuskan untuk berhijrah, Teungku Chik di Awe Geutah membawa banyak bekal. Salah satunya beliau juga membawa banyak air zamzam yang langsung dari Arab.
Baca Juga: Prof. Omar Yaghi, Seorang Pengungsi Palestina yang Menangkan Hadiah Nobel Bidang Kimia
Setelah menetap di Awe Geutah, dan banyaknya orang yang menginginkan air ini, namun semakin hari stok semakin berkurang, maka Teungku Chik di Awe Geutah memutuskan untuk menggali sumur di dekat tempat tinggalnya. Kemudian setelah menggali, dituangkannya lah sisa persedian air zamzam ke dalam sumur tersebut.
Hingga saat ini air di sumur itu tidak pernah kering. Dan hingga saat ini pula air dalam sumur tersebut dijadikan penawar untuk segala penyakit oleh warga di kawasan sekitar.
Ketika ada warga yang ingin mengambil air dari sumur kalut, maka harus meminta izin terlebih dahulu pada ahli waris Teungku Chik di Awe Geutah, karena saat setelah mengambil air ini akan dibacakan doa-doa terlebih dahulu. Saat ini peninggalan Teungku Chiek di Awe Geutah sudah berada pada generasi ke-7. [Cut Salma H.A]
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Sunan Ampel, Pelita Peradaban Islam di Tanah Jawa






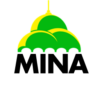
























 Mina Indonesia
Mina Indonesia Mina Arabic
Mina Arabic Mina Preneur
Mina Preneur