Dari Kamp Pengungsi Markazi di Djibouti, Hafsa (bukan nama sebenarnya) mengatakan bahwa dia merasa terjebak.
Perang memaksanya meninggalkan rumahnya di Yaman ke Djibouti bersama suaminya tiga tahun lalu.
Sedikit peluang atau harapan untuk bisa kembali telah membuatnya gelisah di kamp pengungsian terpencil yang jaraknya lebih dari 200 km dari ibu kota Djibouti dan hanya 32 km dari pantai barat Yaman.
Situasi itu telah menciptakan ketegangan antara Hafsa yang berusia 36 tahun dengan suaminya. Tetapi karena dia seorang wanita, dia mengaku dirinya tidak memiliki saluran untuk berbagi perjuangannya.
Baca Juga: Bulan Solidaritas Terhadap Rakyat Palestina
Kondisi kamp dan cuaca yang buruk di dekat desa nelayan, suami yang menganggur dan kurangnya pendapatan, menjadi perselisihan.
Hafsa memiliki tiga anak, satu anak perempuan dari suaminya yang sekarang dan dua anak yang lebih besar dari suaminya ketika tinggal di Yaman.
Wajahnya yang dilingkari jilbab tampak tidak bergaris, membuatnya terlihat lebih muda dari usianya sekarang.
“Saya tidak dapat berbicara dan mengungkapkan perasaan saya kepada orang lain karena masalah atau perselisihan antara saya dan suami mungkin menjadi lebih rumit,” katanya kepada wartawan Al Jazeera dengan suara tegang sebagai gambaran besarnya rasa frustasi yang dirasakannya.
Baca Juga: Di Bawah Langit yang Terkoyak: Kisah Pengkhianatan Terhadap Kemanusiaan di Tanah Palestina
Dia mengungkapkan bahwa para pengungsi lainnya disiksa oleh suami mereka, tetapi mereka takut berbicara karena stigma yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga.
“Kami menderita tradisi,” kata Hafsa. “Sebelum perang, kami menderita banyak masalah, banyak masalah dari masyarakat itu sendiri di Yaman, orang-orang dan tekanan dari tradisi. Perang datang hanya untuk mendorong kami keluar ke Djibouti, tetapi ini adalah tempat yang salah,” katanya. “Kami merasa lemah dan mudah diserang.”
Hafsa adalah salah satu dari ribuan orang Yaman yang melarikan diri ke Djibouti selama lebih dari tiga tahun perang di Yaman.
Perang antara pemerintah Yaman yang didukung oleh koalisi pimpinan Arab Saudi dengan pemberontak Houthi yang didukung Iran, hingga saat ini telah memaksa lebih dari 40.000 warga Yaman melakukan perjalanan berbahaya melintasi Selat Bab-El-Mandeb yang dikenal sebagai Gerbang Air Mata karena telah menelan banyak nyawa migran dan pengungsi.
Baca Juga: Menetapi Jama’ah, Menjaga Diri dari Zaman Penuh Luka
Selat Bab-El-Mandeb menghubungkan Laut Merah dan Teluk Aden di sepanjang pantai timur Djibouti.
Di puncaknya, ada lebih dari 7.000 warga Yaman yang tinggal di Kamp Markazi. Pada Mei 2018, jumlah itu menyusut menjadi kurang dari 2.000.
Kota tenda kecil yang diwarnai oleh debu yang mengepul dari lanskap yang kering dan gersang di musim panas, saat ketika suhu secara teratur meningkat menjadi 40 derajat Celcius di musim panas.
UNHCR dan bendera Djibouti tersentak dalam angin panas di atas gerbang. Lampu sorot listrik digantung dengan kawat berkarat, tetapi menurut mereka di kamp, listrik sering tidak berfungsi.
Baca Juga: Dialog dan Experiential Learning Pada Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidr
Takut melaporkan pelecehan

Pengungsi wanita Yaman di Kamp Markazi di Djibouti. (Foto: dok. IB Times)
Pengungsi memberi tahu Al Jazeera bahwa kondisinya buruk dengan uang, makanan, pekerjaan atau harapan masa depan yang terbatas. Namun bagi wanita, mereka bisa menjadi lebih buruk.
Baca Juga: 14 Poin Krusial KUHAP Baru, Publik Soroti Risiko Pelemahan Hak Asasi
Kelompok-kelompok bantuan dan LSM-LSM lain di kamp mengatakan, perempuan dapat menghadapi pelecehan dalam rumah tangga, fisik dan bahkan seksual.
Hampir tidak ada data tentang kekerasan berbasis gender terhadap pengungsi di Djibouti. UNHCR tidak mencatat insiden di kamp sejak dimulai pada bulan April 2015.
Kepala lembaga di Djibouti mengatakan bahwa laporan terbaru dari petugas perlindungan senior yang mewawancarai seorang penduduk perempuan menemukan tidak ada kekerasan berbasis gender seksual, kecuali satu contoh sodomi antara anak-anak.
Tetapi para profesional dan pengungsi mengatakan, perempuan harus terlebih dahulu mengatasi stigma budaya dan ketakutan akan dampak untuk melaporkan kekerasan dan pelecehan.
Baca Juga: Indonesia dan Masa Depan Hutan Tropis Dunia, Langkah Baru Memimpin Konservasi
“Ada banyak kasus kekerasan di kamp yang terjadi, tetapi para wanita tidak suka mengeluh karena mereka takut ketika mereka kembali ke Yaman, tidak seorang pun akan menerima mereka dan anak-anak mereka sebagai wanita yang diceraikan,” kata Hafsa.
Sebuah laporan UNHCR dari Oktober 2017 mengatakan bahwa meskipun dibentuk komite pengungsi untuk mengatasi kekerasan berbasis gender, komunitas pengungsi Yaman lebih cenderung mengikuti tradisi dan sering naik banding ke kode hukum tradisional daripada yang sipil.
Menurut Dina Cihimba Rehema, pejabat perlindungan UNHCR di Markazi, masalahnya terletak pada kenyataan bahwa wanita sering merasa seperti mereka tidak dapat berbicara tentang situasi mereka.
“Kami harus memperkuat kepekaan bagi wanita untuk merasa bebas dan membuat mereka mudah untuk berbicara tentang apa yang mereka hadapi,” katanya. “Kami harus mencoba mengubah mentalitas.”
Baca Juga: Ancaman Sunyi di Balik Evakuasi Warga Gaza Berkedok Kemanusiaan
Mendidik konselor komunitas
Setiap hari, Muna Khalik, pengungsi lain yang tinggal di Kamp Markazi, membuka pusat konseling yang bertempat di sebuah trailer logam tepat di dalam pintu masuk kamp.
Pusat konseling ini dijalankan oleh UNFD, LSM Djibouti yang bertanggung jawab atas perlindungan perempuan di kamp. Pusat ini memiliki satu anggota staf dan melatih serta mempekerjakan para pengungsi seperti Khalik sebagai penasihat.
Baca Juga: Ketika Pelukan Anak Jadi Obat Lelah
Pusat konseling itu menerima setidaknya empat kasus kekerasan domestik setiap bulan dan dilaporkan langsung ke kantor pusat UNFD.
Organisasi itu mengatakan, pelecehan itu terutama bersifat ekonomi ketika pencari nafkah laki-laki menahan uang dari istrinya dan menciptakan ketegangan dalam keluarga dan bisa juga fisik atau seksual. Laporan mereka ke pusat konseling bersifat rahasia dan cerita detail tentang kasus merka tidak dapat dibagikan ke publik.
Asma Moustapha, Direktur Markazi yang bekerja untuk agen pengungsi pemerintah, mengatakan bahwa ketika pusat konseling pertama kali dibuka tiga tahun lalu, tidak ada wanita yang datang karena stigma tersebut.
“Dalam mentalitas mereka, mereka berpikir kantor hanya untuk masalah perceraian. Mereka tidak berpikir itu bisa membantu mereka dan masalah mereka,” kata Moustapha. “Sebelumnya, suami tidak mau membiarkan mereka pergi ke kantor karena dia pikir itu akan menghancurkan pernikahannya dan keluarganya.”
Baca Juga: Kritik Radikal Ilan Pappe terhadap Proyek Kolonial Israel
Karena wanita merasa lebih nyaman berbagi di sesama komunitas mereka sendiri, UNFD melatih wanita pengungsi untuk menjadi konselor. (AT/RI-1/P1)
(Oleh: Mallory Moench di Al Jazeera)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Pentingnya Narasi dan Literasi dalam Perjuangan Palestina









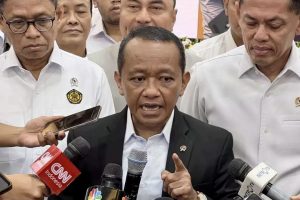

























 Mina Indonesia
Mina Indonesia Mina Arabic
Mina Arabic Mina Preneur
Mina Preneur