Oleh Lili Ahmad, Manajer MINA Publishing House
Pada setiap fragmen waktu yang berlalu, selalu ada peristiwa-peristiwa sakral yang hidup dalam ingatan kolektif manusia, seperti lompatan-lompatan gambar bergerak di layar kaca. Salah satunya adalah peristiwa lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam, kelahiran Sang Nabi yang menggetarkan jiwa dan mengobarkan api spiritual dalam setiap insan yang mencintainya. Oleh karenanya, bagi sebagian Muslim peristiwa kelahiran Sang Nabi ini adalah momen penting yang layak untuk dirayakan, baik sebagai simbol kegembiraan dan kebahagiaan, maupun sebagai ungkapan rasa syukur serta ucapan selamat datang kepada manusia terbaik yang pernah Allah Subhanahu wata’ala ciptakan tersebut.
Namun, yang paling menarik, Perayaan Maulid Nabi lebih dari sekadar ritual keagamaan, Maulid Nabi adalah panggung tempat simbol-simbol berkumpul, berbicara, dan mengukir makna dalam kehidupan sosial. Dalam pandangan sosiologi interaksionisme simbolik, Maulid Nabi bukan hanya perayaan, melainkan tarian lembut dari berbagai makna yang terjalin dalam interaksi antarindividu dan masyarakat.
Jika kita memandang Maulid Nabi dengan kacamata sosiologi tradisional, kita mungkin hanya melihatnya sebagai institusi sosial yang merayakan kelahiran seorang tokoh besar. Namun, interaksionisme simbolik mengajak kita melihat lebih dalam—ke dalam hati setiap individu yang hadir dalam perayaan itu, ketika makna terbentuk melalui interaksi simbolis yang terus-menerus. Setiap shalawat yang dilantunkan, setiap lantunan pujian yang menggema, dan setiap ritual yang dijalankan tidak hanya sekadar tindakan mekanis. Semua itu adalah simbol, jalinan makna yang menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta, dengan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alahi wasallam, dan dengan sesama.
Baca Juga: Peluncuran Kalender Hijrah Global: Langkah Strategis Menyatukan Umat Islam
Ketika seorang jamaah menyenandungkan Shalawat Nabi, bukan hanya kata-kata yang terucap dari bibirnya. Dalam perspektif interaksionisme simbolik, dia sedang menghidupkan simbol cinta, hormat, dan pengabdian kepada sosok yang lebih besar dari dirinya. Shalawat itu adalah cerminan, sebuah interaksi antara dirinya dan Sang Nabi, walaupun mereka terpisah oleh ruang dan waktu. Melalui lisan, seorang hamba berusaha mendekati sosok agung yang pernah hidup ribuan tahun lalu, membangun kembali jembatan spiritual yang tak pernah benar-benar hilang.
Dalam kerumunan perayaan Maulid Nabi, kita menemukan interaksi yang lebih kompleks. Setiap individu datang membawa pemaknaannya sendiri—mungkin sebagai bentuk cinta yang mendalam kepada Sang Nabi, mungkin sebagai upaya untuk merasa terhubung dengan komunitas Muslim, atau mungkin sekadar tradisi yang diwariskan turun-temurun. Namun, ketika mereka bersama-sama, semua makna itu bertemu dan menciptakan simbol kolektif. Suasana yang terbentuk bukan hanya karena kegiatan fisik atau ritual semata, melainkan karena makna-makna yang dibentuk oleh setiap individu melalui interaksi mereka. Di sinilah letak keunggulan interaksionisme simbolik dalam melihat Maulid Nabi: bahwa setiap tindakan, setiap tatapan, setiap nyanyian, adalah sebuah simbol yang membangun dan memperkuat identitas bersama.
Lebih dalam lagi, simbol-simbol dalam perayaan Maulid Nabi mengalir melalui waktu, menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Ketika para ulama atau para ustadz menceritakan kisah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam, cerita itu bukan sekadar sejarah, melainkan sebuah drama hidup yang terus berulang dalam hati setiap pendengarnya. Ini adalah simbol yang hidup, ketika setiap kisah tentang akhlak Sang Nabi menjadi cermin yang membuat setiap individu merenungkan dirinya sendiri. Dalam bahasa para pujangga, Maulid Nabi adalah cermin jiwa, tempat kita melihat pantulan diri kita dalam sosok yang sempurna.
Dalam pemikiran Maulana Jalaludin Rumi misalnya, Maulid Nabi mendapatkan dimensi yang lebih dalam dan spiritual. Rumi, dengan kebijaksanaan sufistiknya, melihat Maulid Nabi sebagai perayaan cinta dan penghubung antara jiwa manusia dan Tuhan. Dalam puisi-puisinya yang memukau, Rumi sering kali menggambarkan cinta sebagai jalan menuju pencerahan, dan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam adalah perwujudan dari cinta ilahi yang sempurna.
Baca Juga: Kutukan Dekade ke-8, Isyarat Runtuhnya Negara Yahudi
Rumi menulis, “Setiap saat adalah permulaan dari waktu baru, dan setiap saat adalah kesempatan untuk bertemu dengan Yang Terkasih.” Maulid Nabi, dalam pandangan Rumi, adalah momen ketika setiap individu memiliki kesempatan untuk terhubung kembali dengan cinta ilahi yang dicontohkan oleh Sang Nabi. Dalam setiap syairnya, Rumi menekankan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam adalah simbol cinta yang murni dan tanpa syarat, dan melalui perayaan Maulid Nabi, umat Islam diundang untuk memasuki dimensi cinta tersebut dengan lebih dalam.
Rumi juga menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam spiritualitas. Dalam konteks Maulid Nabi, ini berarti bahwa perayaan bukan hanya tentang ritual eksternal, melainkan tentang bagaimana setiap individu merasakan kehadiran Sang Nabi dalam diri mereka sendiri. Maulid Nabi adalah waktu untuk mengalami cinta dan kerinduan yang mendalam, untuk merasakan kehadiran Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam dalam setiap aspek kehidupan, dan untuk membiarkan cinta ilahi itu mengubah hati dan jiwa.
Dalam pandangan Rumi, setiap simbol dalam Maulid Nabi—baik itu shalawat, doa, atau ritual lainnya—adalah jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang cinta dan spiritualitas. Rumi mengajarkan bahwa melalui tindakan sederhana seperti berdoa atau berzikir, kita dapat mencapai hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan dan dengan Sang Nabi. Maulid Nabi, dalam tafsir Rumi, adalah kesempatan untuk menyelami lautan cinta yang tiada batas, untuk merasakan getaran cinta yang melintasi waktu dan ruang, dan untuk membiarkan diri kita diubah oleh kehadiran ilahi.
Subjektifitas juga hadir dalam perayaan Maulid Nabi. Bagi sebagian orang, Maulid Nabi adalah cara untuk memperdalam spiritualitas, sebuah perjalanan batin yang membawa mereka lebih dekat kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wata’ala. Namun, bagi yang lain, ia adalah waktu untuk berbagi dengan komunitas, memperkuat hubungan sosial, dan merasakan kebersamaan yang hangat. Simbol-simbol yang digunakan dalam perayaan ini—dari bendera, bunga, hingga lampu hias—mewakili beragam makna yang berbeda bagi setiap orang. Tidak ada satu makna yang absolut; semua tergantung pada bagaimana individu tersebut menafsirkan dan berinteraksi dengan simbol-simbol yang ada.
Baca Juga: Bila Mata Tak Terjaga, Hati Bisa Ternoda
Di dalam sanubari setiap individu, Maulid Nabi bukan sekadar peringatan historis. Ia adalah simbol hidup yang terus-menerus berdenyut dalam jiwa mereka yang terlibat di dalamnya. Dalam setiap interaksi, baik itu dalam keheningan doa maupun dalam riuhnya lantunan shalawat, ada makna yang saling berkelindan, menghubungkan dunia material dengan yang immaterial, dunia nyata dengan dunia simbolik. Dan dalam keheningan malam setelah perayaan usai, setiap hati yang hadir dalam Maulid Nabi itu akan kembali pada dirinya sendiri, merenungi makna-makna yang telah terjalin dalam interaksi mereka dengan Sang Nabi dan sesama umat.
Maulid Nabi, dalam pandangan interaksionisme simbolik dan kebijaksanaan Maulana Jalaludin Rumi adalah ruang saat manusia, dengan segala keterbatasannya, mencoba menjangkau yang Ilahi melalui simbol-simbol yang mereka bangun bersama. Ini adalah cermin jiwa, tempat kita semua berkumpul, melihat, dan menemukan diri kita sendiri dalam keagungan Sang Nabi.[]
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Kesewenang-wenangan Pendirian Gereja: Fakta, Realita, dan Suara Umat yang Terpinggirkan






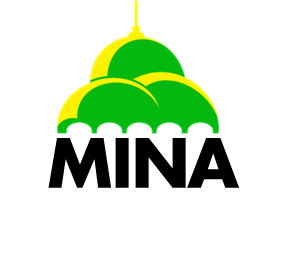






























 Mina Indonesia
Mina Indonesia Mina Arabic
Mina Arabic Mina Preneur
Mina Preneur