Peran Negara di Bidang Ekonomi
Dari sepuluh tanggungjawab utama negara yang disebut Al Mawardi, tiga diantaranya menyangkut aspek ekonomi. Pertama, menciptakan keamanan dalam negeri sehingga warga dapat mencari penghidupan dan bepergian dengan aman, jiwa dan hartanya. Kedua mengumpulkan fai dan zakat sesuai syariat. Ketiga menghitung dengan adil hak-hak baitul maal dan mendistribusikannya segera.[1]
Dalam bukunya Adab al Diin wa al Dunya ia menegaskan kembali peran negara bidang stabilitas keamanan terkait perekonomian di salah satu dari tujuh peran pemerintah yakni menyediakan infrastruktur transportasi dan pemanfaatan sumber daya alam dengan optimal. Kedua hal itu penting untuk menciptakan pemerataan kemakmuran negeri.[2]
Pandangan tersebut menjadi bagian penting dari berdirinya negara. Pendirian negara, menurut Al Mawardi, bertujuan untuk memelihara agama dan dunia. Pemenuhan kebutuhan materil dan spiritual masyarakat, dengan demikian, menjadi tanggungjawab negara. Pemerintah dianggap telah menunaikan tugas utama itu bila tercipta masyarakat yang salih dan sejahtera secara luas.
Baca Juga: IKAPI Gelar Islamic Book Fair 2025, Catat Agendanya
Aktifitas Ekonomi
- Produksi sebagai sumber pendapatan negara dan publik
Negara, seperti yang telah disebutkan, bertanggungjawab pada urusan agama dan kesejateraan rakyatnya. Untuk mencapai tujuan kesejahteraan itu negara harus menempatkan secara adil antara sumber kekayaan negara dan publik. Negara wajib memisahkan dan mengatur antara hak-hak negara dengan hak-hak warganya.
Meski ada hak-hak kekayaan milik negara, namun pemerintah wajib menyalurkan seluruhnya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
Keberadaan baitul maal, dalam pandangan Al Mawardi, penting dalam rangka pengelolaan dua sumber kekayaan di atas. Sumber-sumber pendapatan baitul maal menurut Al Mawardi diantaranya zakat, fai dan ghanimah. Dari ketiga sumber itu yang merupakan hak baitul maal :
Baca Juga: Semangat dan Haru Iringi Pemberangkatan Kloter Pertama Haji dari Surabaya
- Zakat harta yang tampak seperti sayur-sayuran atau peternakan.
- Seperlima harta ghanimah atau fai yang menjadi bagian Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam di mana usai wafatnya bagian itu sepenuhnya ditujukan untuk kepentingan umum.
- Fai yang mencakup jizyah, kharaj dan ‘
Ketiga sumber pendapatan itu menjadi hak pemerintah dalam mengatur tujuan distribusinya selama untuk kemaslahatan umum. Al Mawardi menyebut tiga sumber kekayaan itu diatur alokasinya berdasarkan ijtihad pemerintah.
Sumber kekayaan yang menjadi milik warga dan bukan hak pemerintah menguasainya adalah :
- Zakat harta yang tidak tampak seperti emas dan perak di mana pemiliknya berhak mendistribusikannya langsung ke ashnaf
- Seperlima harta ghanimah atau fai yang menjadi bagian kerabat Nabi shallallahu’alaihi wa sallam, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil.
- Empat perlima ghanimah yang menjadi milik para ghanimin yakni mereka yang turut berperang hingga berhasil meraih ghanimah.[3]
Warga selain berhak atas sumber-sumber pendapatan tersebut juga berhak atas pemanfaatan kekayaan alam di tanah milik mereka melalui aktifitas produksi yang legal. Dua dari empat aktifitas produksi manusia menurut Al Mawardi terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam, yakni pertanian dan peternakan.[4]
Dua aktifitas produksi lainnya adalah perdagangan dan industri. Al Mawardi memasukkan profesi-profesi teknokrat, kepegawaian dan buruh ke dalam aktifitas industri. Ia membagi industri menjadi tiga : industri pemikiran, industri kerja dan gabungan antara keduanya. Dari ketiganya industri pemikiran menempati hirarki tertinggi.
Baca Juga: Indonesia Alihkan Ekspor ke Eropa dan Australia Hadapi Tarif Tinggi dari AS
Tanah sebagai sumber pendapatan utama, dalam pandangan Al Mawardi, harus dikelola secara adil. Saat membahas kharaj ia meletakkan titik keadilan penepatan pajaknya pada penilaian yang memperhatikan empat unsur : kesuburan tanah, jenis tanaman, sistem irigasi dan jarak antara tanah dengan pasar.[5]
Sementara itu metode penetapannya ada tiga pilihan. Pertama berdasarkan ukuran tanah, baik ditanami atau tidak. Kedua luas tanah yang ditanami. Dan ketiga berdasarkan hasil produksi tanaman.
Al Mawardi sangat mendorong aktifitas produksi yang dilakukan manusia dilakukan dalam ukuran-ukuran yang sehemat mungkin. Ia membuat tingkatan pola produksi manusia dan menempatkan mereka yang bekerja sekedar untuk memenuhki kebutuhan primernya dalam hirarki tertinggi dan paling mulia. Di bawahnya adalah mereka yang bekerja namun tak mampu mencukupi kebutuhan primernya baik karena malas, tawakkal ataupun zuhud.
Adapun mereka yang bekerja secara berlebih, oleh Mawardi dibagi menjadi tiga alasan; syahwat, distribusi kebaikan dan memperkaya diri.[6]
Baca Juga: Airlangga: Tarif Impor AS ke Produk Indonesia Bisa Tembus 47 Persen
Penempatan pola produksi sehemat mungkin di tingkatan tertinggi merepresentasikan pemikiran Al Mawardi tentang pentingnya distribusi kekayaan dan produksi yang berkesinambungan.
Di level pemerintah Al Mawardi memandang negara harus meletakkan prinsip pembangunannya pada sistem yang berkelanjutan. Program pembangunan tidak boleh berhenti pada satu generasi tanpa mempertimbangkan kebutuhan generasi berikutnya.
Dalam pemanfaatan sumber daya alam peran generasi pertama adalah mengeksplore, mengelola dan memproduksinya secara wajar dan hemat. Generasi kedua berperan menjaganya tetap dapat diproduksi secara wajar. Dan generasi ketiga memperbaiki kerusakan-kerusakan yang timbul akibat pola produksi dalam jangka panjang.[7]
- Distribusi
Baitul maal, dalam pandangan Al Mawardi, menempati posisi strategis untuk mencapai distribusi pendapatan negara secara merata. Melalui baitul maal pemerintah pusat dapat mengatur distribusi kekayaan di masing-masing profinsi sesuai kebutuhannya. Jika kebutuhan ekonomi suatu profinsi telah terpenuhi, masyarakatnya hidup sejahtera dan terjadi surplus pendapatan, Pusat berhak menarik kelebihan itu untuk dialokasikan ke profinsi lain yang defisit.[8]
Baca Juga: Google Akui Kesalahan Data Nilai Tukar Rupiah ke Dolar AS
Selain itu melalui baitul maal pendapatan negara dari berbagai sumber akan disimpan dalam pos-posnya masing-masing dan dibelanjakan sesuai alokasinya masing-masing. Jika dana satu pos tidak mencukupi pembiayaan kebutuhan yang direncanakan, pemerintah dapat meminjam dari pos lain.
Pos pendapatan zakat misalnya harus didistribusikan di profinsi tempat zakat itu diambil. Pengalihan distribusi pendapatan zakat ke profinsi lain diizinkan apabila seluruh golongan mustahik zakat di profinsi pertama telah menerima haknya secara memadai. Dan profinsi yang berhak menikmati surplus pendapatan zakat profinsi pertama adalah yang terdekat dengannya.
Upaya pengentasan kemiskinan melalui zakat ditentukan usai pemerintah telah menetapkan hadd kifayah. Menurut Al Mawardi harta zakat untuk fakir miskin hanya diberikan sekedar untuk membebaskan mereka dari kemiskinan.
Al Mawardi memandang bahwa untuk menjamin distribusi harta baitul maal secara adil, lancar dan merata negara membentuk dewan hisbah. Fungsi dewan hisbah diantaranya adalah menentukan kebutuhan publik suatu wilayah dan membuat anggarannya.[9]
Baca Juga: Google Eror? 1 Dolar AS Jadi Rp8.170,65
Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tercapainya tujuan distribusi yang adil ditentukan melalui faktor-faktor berikut :
- Sumber kekayaan alam suatu wilayah
- Kebutuhan infrastruktur umum di wilayah itu
- Batasan maksimal kesejahteraan masyarakatnya
- Pembagian harta baitul maal secara adil berdasarkan tiga aspek di atas
- Konsumsi
Al Mawardi memandang kebutuhan manusia terhadap materi didasarkan pada fitrahnya sebagai makhluk yang lemah. Allah menciptakan manusia dengan fitrahnya yang cenderung rakus terhadap dunia dan di saat bersamaan Dia jadikan manusia makhluk yang lemah. Hikmah dari dua tabiat dasar ini agar manusia tidak berlebihan dalam memuaskan hajat duniawinya dan menghindarkannya dari sifat sombong disebabkan kemampuanya meraih kekayaan.[10]
Harta yang diperoleh dan dikonsumsi harus bertujuan untuk membantu meraih kebutuhan akhirat. Ukuran kekayaan, menurutnya, dilihat dari seberapa banyak harta yang diinfakkan untuk akhirat. Ia mendorong agar manusia mencari dan mengumpulkan harta sebanyak mungkin namun tidak untuk dinikmati sekedar memuaskan nafsu melainkan untuk menginvestasikannya di kehidupan akhirat.[11]
Ia menilai manusia tidak boleh bergantung pada dunia. Mencintai dunia adalah tercela dan mencari-carinya adalah keburukan. Cinta dunia yang tercela adalah saat manusia mencari dan mengkonsumsinya melebihi batas kebutuhannya.
Baca Juga: Truk Sengaja Tabrak Kerumunan saat Pesta Tahun Baru di AS, 10 Orang Tewas
Dari pandangan tersebut tampak sekali bahwa Islam tidak melihat konsumsi sebagai upaya penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan setinggi-tingginya. Islam justru menilai konsumsi sebagai aktifitas memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani.
Selain itu pemenuhan kebutuhan akan masa depan akhirat hanya bisa diraih manakala seorang muslim meninggalkan hidup bermewah-mewahan dan menghindari konsumsi barang dan jasa yang diharamkan. Seorang muslim hanya berhak menikmati hartanya sekedarnya saja. Selebihnya pendapatan yang ia peroleh menjadi hak milik orang lain yang wajib disalurkan.
Uraian di atas menjelaskan bahwa dalam sistem ekonomi Islam konsumsi bukan hanya menjadi aktifitas ekonomi individualis dan duniawi semata. Sistem ekonomi Islam sarat dengan nilai-nilai ukhrawi dan akhlak. Perilaku konsumsi dalam Islam tidak boleh konsumtif dan permisif.
Baca Juga: Hadiri Indonesia-Brazil Business Forum, Prabowo Bahas Kerjasama Ekonomi
[1] Al Ahkaam al Sulthaniyah wa al Wilayat al Diniyah, Abul Hasan ‘Ali Al Mawardi, hlm 22 – 23.
[2] Adab al Diin wa al Dunya, Abul Hasan ‘Ali Al Mawardi, hlm 222.
[3] Al Ahkaam al Sulthaniyah wa al Wilayat al Diniyah, hlm 277 – 279.
[4] Adab al Diin wa al Dunya, hlm 337 – 348.
Baca Juga: Rupiah Berpotensi Melemah Efek Konflik di Timur Tengah
[5] Al Ahkaam al Sulthaniyah wa al Wilayat al Diniyah, hlm 189.
[6] Adab al Diin wa al Dunya, hlm 343 – 348.
[7] Ibid, hlm 146.
[8] Al Ahkaam al Sulthaniyah wa al Wilayat al Diniyah, hlm 277 – 279.
Baca Juga: Komite Perlindungan Jurnalis Kutuk Israel atas Tebunuhnya Tiga Wartawan di Lebanon
[9] Ibdi, hlm 281.
[10] Adab al Diin wa al Dunya, hlm 211.
[11] Ibid, hlm 213
(A2/P2)
Mi’raj News Agency (MINA)














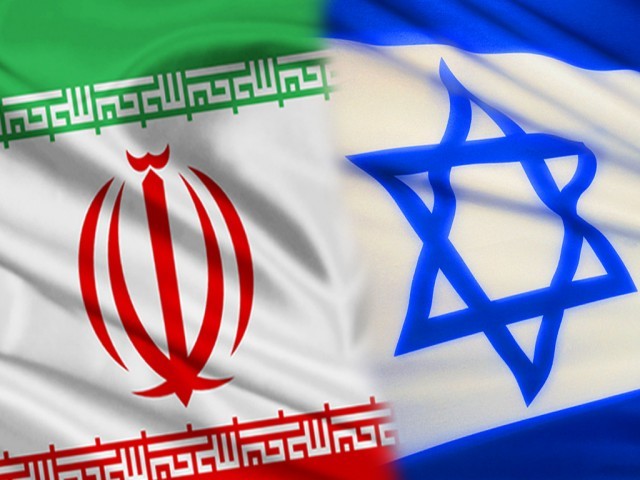





















 Mina Indonesia
Mina Indonesia Mina Arabic
Mina Arabic Mina Preneur
Mina Preneur