Oleh Arini Amarta, Mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Shuffah Al-Qur’an Abdullah Bin Mas’ud Lampung
Stigma intoleransi yang disematkan kepada umat Islam sampai saat ini merupakan bentuk ketidakadilan bahkan dinilai bagian dari upaya mendiskreditkan Islam sebagai agama Rahmatan Lil A’lamin, yang dirasakan rahmatnya bukan hanya oleh manusia tapi seluruh isi bumi.
Inilah yang dijadikan “dalil” oleh mereka yang tidak menyukai Islam, dengan menuduh Islam merupakan agama yang mengajarkan terorisme. Karena menurut mereka, Islam mengajarkan intoleransi yang menjadi cikal-bakal orang menjadi teroris. Menurut mereka, awalnya intoleran, setelahnya radikal, dan kemudian menjadi teroris. Tentu ini merupakan tuduhan tidak berdasar. Padahal, Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk bertoleransi cinta kedamaian dan keselamatan terhadap sesama umat manusia. Bahkan Islam memberi batasan yang jelas “Bagimu agamamu, bagiku agamaku”.
Terlebih, Islam melihat manusia itu mulia, apapun agamanya, etnis, suku atau apapun, karena memang Allah ciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kita bisa saling mengenal. Begitulah dijelaskan di dalam kitab suci umat Islam, Al-Qur’an. Bahkan tak hanya yang hidup, sudah menjadi jenazahpun tetap dimuliakan dan dihormati.
Baca Juga: Persatuan sebagai Solusi Masalah Palestina
Di dalam beberapa ayat Al-Qur’an, Allah memerintahkan umat Islam bahkan menyukai untuk berbuat adil dan baik kepada orang kafir yang tidak memerangi muslim. Allah menggambarkan toleransi itu salah satunya pada QS. Al-Mumtahanah ayat 8-9:
لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ
إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ
ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
Baca Juga: Kemenangan Iran atas Zionis Israel
Tidaklah Allah melarang kamu terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu pada agama dan tidak mengusir kamu dari kampong halaman kamu, bahwa kamu berbaik dengan mereka dan berlaku adil terhadap mereka; sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berlaku adil (8), Yang dilarang kamu hanya terhadap orang-orang yang memerangi kamu dan mengusir kamu dari kampung halaman dan mereka bantu atas pengusiranmu itu, bahwa kamu menjadikan mereka teman. Dan barang siapa yang berkawan dengan mereka, maka itulah orangorang yang aniaya (9).
Adalah Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan Buya Hamka dengan kitab Tafsir Al-Azhar yang diselesaikannya saat di penjara pada zaman Soekarno. Dalam menafsirkan ayat di atas, Hamka sebagai pribadi yang tegas memegang prinsip-prinsip keagamaan lebih awal mengedepankan latar historis turunnya ayat tersebut (Asbab Nuzul).
Menurutnya, setelah perjanjian hudaibiyah banyak orang Arab Quraisy yang menemui keluarganya yang telah berhijrah bersama Nabi ke Madinah. Diantaranya adalah Qutailah, Ibu dari Asma’ yang tidak lain adalah bekas istri Abu Bakar. Ketika Qutailah menemui (karena sayang dan rindunya) juga memberikan hadiah kepada Asma’, Asma’ merasa ragu akan pemberian ibunya tersebut, dikarenakan ibunya pada saat itu belum masuk Islam. Hal ini ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat di atas. Dalam Tafsir Al-Azhar, Hamka menyimpulkan ayat diatas dan dua ayat sebelumnya adalah pedoman bagi umat Islam untuk bertoleransi dalam tataran praktis dengan umat agama lain.
Menurutnya, dipersilakan kepada umat Islam untuk bergaul dengan akrab, bertetangga, saling tolong menolong, bersikap adil dan jujur kepada pemeluk agama lain. Tetapi jika ada bukti bahwa pemeluk agama lain itu hendak memusuhi, memerangi dan mengusir umat Islam, maka semua yang diperbolehkan itu menjadi terlarang. Meskipun mereka tidak memusuhi Islam namun membantu dalam memusuhi Islam, memiliki hukum yang sama, juga harus diperangi. Ahli-ahli tafsir menyatakan, ayat ini adalah ayat “Muhkamah” artinya berlaku buat selama-lamanya, tidak dimansukhkan.
Baca Juga: Jihad Itu Lokomotif Perubahan Seorang Muslim
Ketika menjelaskan tafsir ayat ini, Hamka mengkritik keras ucapan sebagian orang yang mengatakan, bagi saya segala agama itu adalah sama saja karena sama-sama baik tujuannya. Terhadap orang-orang semacam ini, Hamka menegaskan pendiriannya: Orang yang berkata begini nyatalah bahwa tidak ada agama yang mengisi hatinya. Kalau dia mengatakan dirinya Islam, maka perkataannya itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Karena bagi orang Islam sejati, agama yang sebenarnya itu hanya Islam.
Hamka memaknai toleransi adalah yang dilandasi oleh kesadaran penuh akan perbedaan fundamental di antara setiap agama dan bukannya dengan berpura-pura tidak melihat perbedaan-perbedaan itu, apalagi dengan berusaha melenyapkannya. Kesadaran akan perbedaan itu akan melahirkan sikap saling menghormati dan tidak saling mencampuri. Dengan begitu, jelas sudah makna Lakum Diinakum Wa Liyadiin.
Pada 1968, umat Islam berhari raya Idul Fitri dua kali, yaitu pada 1 Januari dan 21 Desember 1968. Dekatnya tanggal Hari Raya Idul Fitri tanggal 21 Desember dengan Natal tanggal 25 Desember kemudian menginspirasikan sebagian kepala instansi pemerintah dan menteri untuk mengeluarkan perintah agar perayaan halal bihalal digabungkan dengan Natal menjadi ‘Lebaran-Natal’. Sebagian pejabat mengatakan bahwa demi kesaktian Pancasila, ‘Lebaran-Natal’ ini dapat membantu kita memahami makna toleransi.
Buya Hamka menolak dengan keras toleransi yang semacam itu. Perayaan ‘Lebaran-Natal’ tidak ubahnya sebuah pemaksaan kepada umat beragama agar ikut mendengarkan kajian-kajian keagamaan yang bertentangan dengan pokok-pokok keagamaannya sendiri. Bagi Hamka, yang semacam ini adalah toleransi paksaan dan memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan pandangan sinkretisme.
Baca Juga: Sedekah Sebelum Terlambat: Tadabbur Qur’an Surat Al-Munafiqun Ayat 10
Dalam sebuah khutbah Jum’at di Masjid Agung Al-Azhar, Buya Hamka mengingatkan,”Haram hukumnya bahkan kafir bila ada orang Islam menghadiri upacara natal. Natal adalah kepercayaan orang Kristen yang memperingati hari lahir anak Tuhan. Itu adalah aqidah mereka. Kalau ada orang Islam yang turut menghadirinya, berarti dia melakukan perbuatan yang tergolong musyrik. Ingat, dan katakan pada kawan-kawan yang tidak hadir di sini. Itulah aqidah tauhid kita,” tegasnya dengan suara lantang. Begitu tertulis dalam buku karangan Rusydi Hamka, 1981, berjudul Pribadi dan Martabat Buya Prof.Dr. Hamka.
Itulah sikap Buya Hamka mengenai acara lebaran natal bersama ini, yang berlanjut menjadi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Buya Hamka yang ketika itu menjadi Ketua MUI, memutuskan bahwa haram hukumnya umat Islam merayakan natal. Mendengar fatwa ini, pemerintah melalui Menteri Agama Alamsyah lalu meminta supaya fatwa itu dicabut. Namun Buya Hamka memilih meletakkan jabatannya sebagai Ketua MUI.
Menurut Buya Hamka dalam buku Dari Hati ke Hati Tentang: Agama, Sosial-Budaya, Politik yang diterbitkan 2002, “Semangat toleransi yang sejati dan logis ialah ketika orang Islam berdo’a, orang Kristen meninggalkan tempat berkumpul. Dan Ketika Pastor berdoa kepada Tiga Tuhan, orang Islam keluar”. (A/arn/hlm/wrd/B03).
Mi’raj News Agency (MINA).
Baca Juga: Nuklir, Mudharat dan Manfaatnya dalam Perspektif Al-Qur’an






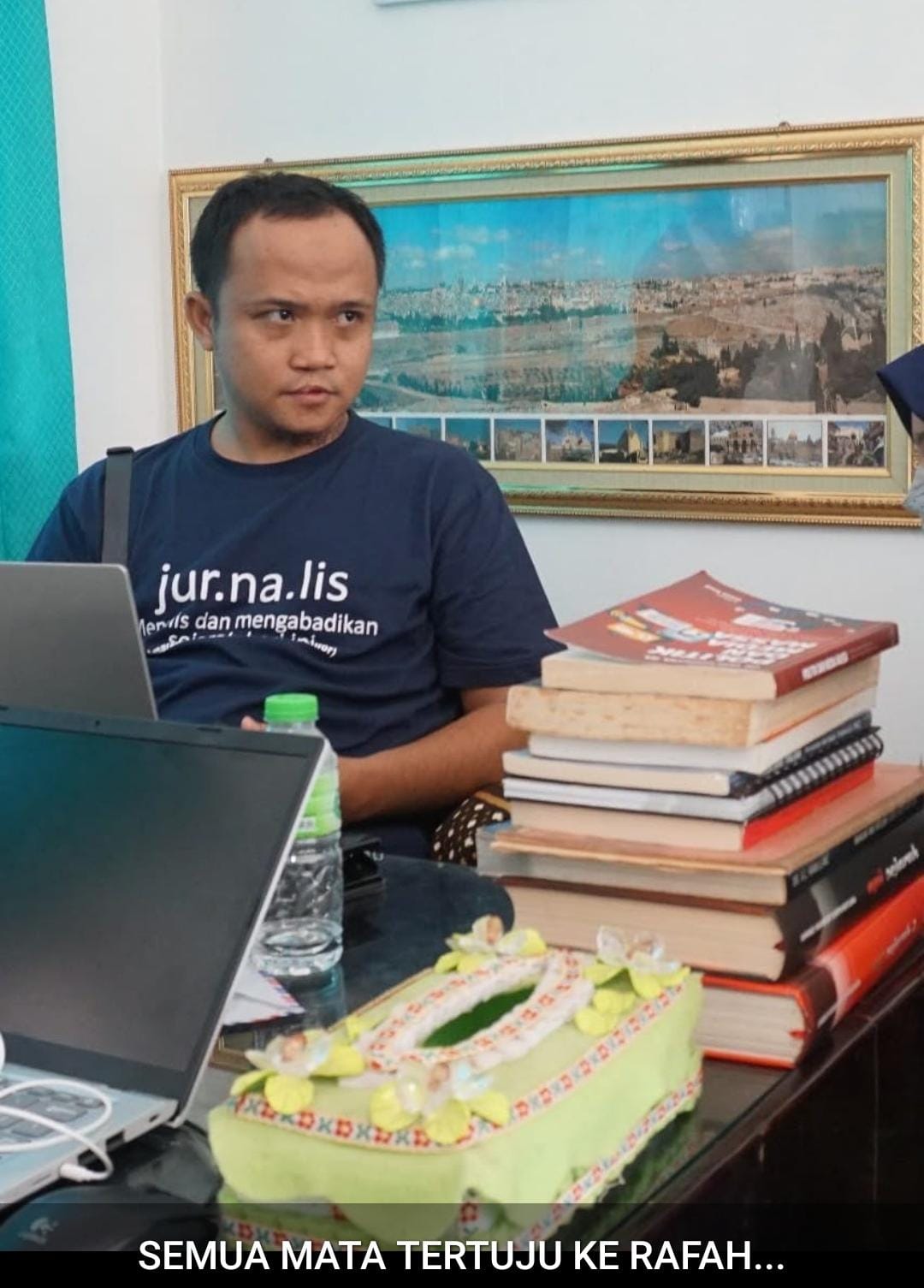






























 Mina Indonesia
Mina Indonesia Mina Arabic
Mina Arabic Mina Preneur
Mina Preneur